Logosentrisme telah menghantui dan mendominasi filsafat barat. Logosentrisme merupakan suatu sistem yang mempercayai adanya kebenaran atau logos transendental yang melampaui dunia fenomena. Logos seolah-olah terungkap dalam konsep-konsep atau teori-teori filsafat. Atau dengan ungkapan lain, konsep atau teori tertentu dalam filsafat dianggap telah menunjukkan suatu kebenaran dan telah mewakili logos. Hal tersebut tercontoh ketika filsafat mereduksi berbagai persoalan ke dalam satu rumusan tunggal yang bersifat dan diterima secara a priori. Ketika rumusan tunggal ini diajukan, kebenarannya pada saat itu juga dianggap universal. Idealisme objektif Plato, rasionalitas dalam Descartes, perjalanan kesadaran Roh dalam pemikiran Hegel merupakan contoh-contoh keinginan filsafat pada keyakinan universal yang sekaligus mengatasi partikularitas. Keyakinan universal ini bergerak lebih jauh menjadi keyakinan kebenaran objektif. Suatu kebenaran yang terbebas dari konteks sejarah, sosial politik, dan perubahan-perubahan lainnya. Semangat objektivitas dan universalitas tadi menjadi latar belakang seorang filsuf menyodorkan suatu “terobosan” filosofis. Terobosan tersebut disodorkan oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Jacques Derrida. Derrida mengenalkan suatu cara membaca teks bernama dekonstruksi. Dekonstruksi menjadi suatu cara baca yang menggoyahkan bahkan meluluhlantakkan semangat objektif dan universalitas tadi. Namun tidak sampai di situ saja, dalam tulisan ini akan sedikit membahas lebih jauh akibat dari dekonstruksi tadi. Akibat yang akan dibahas lebih spesifik merujuk dampak dekonstruksi terhadap diskursus ketuhanan atau teologi.
Sekilas Tentang Dekonstruksi
Dekonstruksi bisa kita anggap sebagai strategi atau cara dalam mengurai teks. Istilah dekonstruksi memiliki kedekatan pengertian dengan istilah “analitis”. Kedua istilah tersebut memiliki arti “mengurai, membuka, melepaskan”. Dekonstruksi oleh karenanya bermaksud untuk mengurai struktur dan pusat makna dalam teks. Secara umum dekonstruksi ingin menunjukkan keberadaan oposisi-oposisi biner implisit dalam teks. Akibatnya, dekonstruksi tidak bermaksud menghancurkan makna dalam teks. Dekonstruksi lebih bertujuan menghancurkan klaim otoritatif yang menganggap satu bentuk pemaknaan lebih benar dibanding pemaknaan lain (Fayyadl, 2005).
Sekurang-kurangnya ada empat hal yang diinginkan oleh dekonstruksi. Pertama, dekonstruksi bermaksud membongkar hierarki metafisik yang bersifat oposisi biner. Contoh oposisi biner misalnya: pribumi/non pribumi, roh/materi, substansi/aksiden, jiwa/badan. Dalam pola oposisi biner, yang pertama biasanya dianggap lebih utama, prinsip, dan niscaya ketimbang yang kedua. Yang kedua sekedar manifestasi, turunan, dan sekunder. Ketiga, dekonstruksi menawarkan strategi untuk menemukan kontradiksi dalam teks. Penemuan tersebut mengarahkan pada pemahaman akan adanya inkonsistensi dalam teks. Keempat, dekonstruksi akan memandang teks dan konteks sebagai alat untuk membuka kemungkinan perubahan baru dalam hubungan yang tak mungkin. Artinya, dekonstruksi tidak membatasi penafsiran dan justru membebaskan penafsiran. Pada akhirnya dekonstruksi mempertajam kreativitas dalam melihat kemungkinan-kemungkinan penafsiran tersebut. Kelima, dekonstruksi menjadikan teks yang semula familiar menjadi asing bagi pembaca. Hal itu terjadi karena makna-makna yang sebelumnya terpinggirkan oleh pusat atau fondasi teks, kini disingkapkan oleh dekonstruksi (Haryatmoko, 2016).
Dari tujuan-tujuan tersebut kita dapat mengetahui bahwa dekonstruksi mengkonfrontasi langsung gaya berpikir filsafat barat. Gaya berpikir di sini mengacu pada gaya berpikir logosentris. Salah satu gaya berpikir logosentris adalah adanya dikotomi subjek-objek. Subjek menjadi dominan dan mengeksploitasi objek. Kedominanan subjek terwujud ketika rasionya menentukan validitas kebenaran. Hal ini mendorong lebih jauh pada apa yang disebut sebagai metafisika kehadiran. Metafisika kehadiran artinya suatu konsep tertentu yang diutarakan subjek seolah sudah mewakili dan merengkuh kebenaran. Kebenaran yang diandaikan absolut, tunggal, dan universal (Santoso dkk, 2016). Pada gilirannya kelak kebenaran sejenis ini menjadi “alat kekerasan epistemik” bagi yang terpinggirkan. Menjadi kebenaran yang meminggirkan segala hal yang tidak sesuai dengannya, menjadi otoriter, dan membentuk rezim kebenaran. Rezim yang membuat patokan, kategori atau standar mana yang bisa disebut benar dan mana yang tidak.
Cara Kerja Dekonstruksi
Kita bisa melihat cara kerja dekonstruksi dengan mengambil contoh kasus hierarki oposisi biner. Dalam pemikiran Claude Levi-Strauss terdapat dikotomi atau oposisi biner antara alam dan budaya. Alam adalah sesuatu yang universal, sedangkan budaya ditentukan oleh norma-norma sosial tertentu, yang berarti partikular. Namun, pada saat yang sama Levi-Strauss berbicara tentang larangan incest. Larangan ini ditentukan oleh norma sosial yang berarti bersifat partikular. Padahal kenyatannya larangan incest bersifat universal karena berlaku hampir di setiap bentuk budaya. Dari sini terlihat bahwa dekonstruksi menggoyahkan pemaknaan dianggap mapan. Budaya dalam dikotomi tersebut nyatanya tidak selalu berarti partikular. Larangan incest menunjukkan hal tersebut, artinya konsep “budaya” tergantung konteksnya. Differance atau secara sederhana artinya “penundaan” adalah istilah yang dikenalkan Derrida untuk menyebut proses dalam contoh tersebut (Haryatmoko, 2016).
Differance menunjukan bahwa pada dasarnya dekonstruksi bekerja dalam teks itu sendiri. Differance sudah selalu menjadi struktur dasar dari setiap teks. Differance bukan sebuah konsep, ia sekedar cara bermain yang mengancam kestabilan teks. Cara bermain yang juga menolak dan mencairkan hierarki atau oposisi yang membentuk pengertian tunggal. Differance mencegah ambisi besar untuk merangkum segala sesuatu ke dalam satu kebenaran tunggal (Al-Fayyadl, 2005). Ada keterkaitan erat antara karakteristik bahasa dan differance. Karakteristik bahasa ini juga lah yang memungkinkan dekonstruksi bekerja. Dekonstruksi bekerja dengan andaian dasar bahwa filsafat barat atau suatu sistem manapun mampu mempertahankan ide yang dianggap kebenaran tunggal karena menekan karakteristik tertentu dari bahasa. Karakter ini antara lain dimensi metaforisnya, ambigu, polisemi, ekuivok, dan serba paradoks dalam dirinya sendiri.
Kita ambil salah satu contoh istilah “subjek”. Pengertian subjek dalam subjek Cogito Cartesian tentu berbeda dengan dengan pengertian subjek dalam tradisi Kristiani. Subjek dalam pemikiran Immanuel Kant misalnya berbeda dengan subjek yang dipahami oleh Jacques Lacan. Yang ingin ditunjukan di sini adalah kesulitan untuk mempertahankan ketunggalan makna dalam istilah tersebut. Misalkan lagi konsep “agama”, konsep ini tentu sulit untuk berdiri sendiri. Karena konsep tersebut terhubung dengan jejaring makna yang terkait dengan metafisika, politik, ekonomi, kekuasaan, sejarah, dan lain-lain (Hardiman, 2015). Namun perlu diingat bahwa dekonstruksi memiliki perbedaan dengan cara atau strategi membaca teks lain. Dalam dekonstruksi, tidak ada makna yang hendak diraih dan diputuskan. Karena setiap penentuan makna dicegah oleh suatu makna yang berjejaring dengan makna yang ingin ditentukan itu. Akibatnya teks selalu terbuka terhadap “yang lain”. Oleh karena itu, dekonstruksi bisa dikatakan membimbing kita untuk melakukan pergantian perspektif terus-menerus.
Jejak Dekonstruksi
Seperti yang telah disinggung di awal, dekonstruksi memiliki akibat terhadap dimensi teologis atau pembicaraan mengenai ketuhanan. Dekonstruksi pada intinya menunjuk pada ketidakmungkinan untuk membicarakan Tuhan. Melalui penjelasan dan cara kerjanya dekonstruksi telah menunjukan ketidakmungkinan untuk mencapai kebenaran. Kebenaran tidak tercapai sebab horizon pemaknaan yang dianggap benar telah hancur atau setidaknya tertunda. Setiap pemaknaan sekurang-kurangnya terpapar cara kerja seperti: di balik hierarkinya, dikembalikan pada sifat bahasa yang polisemi, ambigu, ditunjukkan jejaring dengan makna yang lain, dengan konteks, dan diganti terus-menerus perspektifnya. Makna tersebar ke segala arah tanpa tujuan tertentu, tanpa pernah diputuskan. Dapat dipastikan, konsep tentang Tuhan pun tidak luput dari cara kerja dekonstruksi tersebut.
Tuhan oleh karenanya menjadi yang tak mungkin dibahasakan, melampaui bahasa dan pengetahuan, melampaui kategorisasi, dan tak terjemahkan. Satu-satunya ungkapan ketika berhadapan dengan-Nya hanyalah “saya tidak mengetahui apa-apa”. Ketidaktahuan dan ketakmungkinan total ini adalah konsekuensi tak terhindarkan dari dekonstruksi. Yang Ilahi pada akhirnya menjadi gelap, tak terjamah oleh “kekerasan bahasa” yang kita biasa lakukan. Keadaan semacam ini membawa pada penghayatan Tuhan yang tak terbatas dan di luar jangkauan bahasa manusia. Penghayatan yang tidak sekedar membuntut dogma karena institusi agama yang mewajibkannya. Mempertanyakan, mengkritisi, menggugat, dan menjadikan keimanan sebagai eksperimentasi tanpa henti merupakan penghayatan yang dimaksud. Iman tak pernah menyentuh kata selesai, tak ada iman final, iman yang selalu berproses dalam pengalamannya dengan Yang Ilahi (Al-Fayyadl, 2005).
Dekonstruksi berpijak dari keterbukaan iman kepada masa depan absolut. Pengalaman religius akhirnya menjadi pergumulan diri bersama ketidakpastian radikal, kenyataan yang tak terencanakan dan memungkinankan iman untuk goyah. Dengan pengalaman religius semacam ini, masa depan adalah sesuatu yang disambut karena kedatangan Yang Ilahi. Mengapa Dia harus ditunggu di masa depan? Karena Yang Ilahi melampaui pembatasan kita, melampaui apa yang dibayangkan, sesuatu yang mustahil kita pahami dalam kondisi kekinian (Al-Fayyadl, 2005). Dengan demikian, selalu ada penundaan untuk menamai Yang Ilahi ini, yang mengarah kepada ketakmungkinan, dan lebih jauh menuntut untuk berkata tidak pada setiap konseptualisasi atau penamaan terhadapnya. Dan itu semua menjadikan pembicaraan Tuhan menjadi tak mungkin.


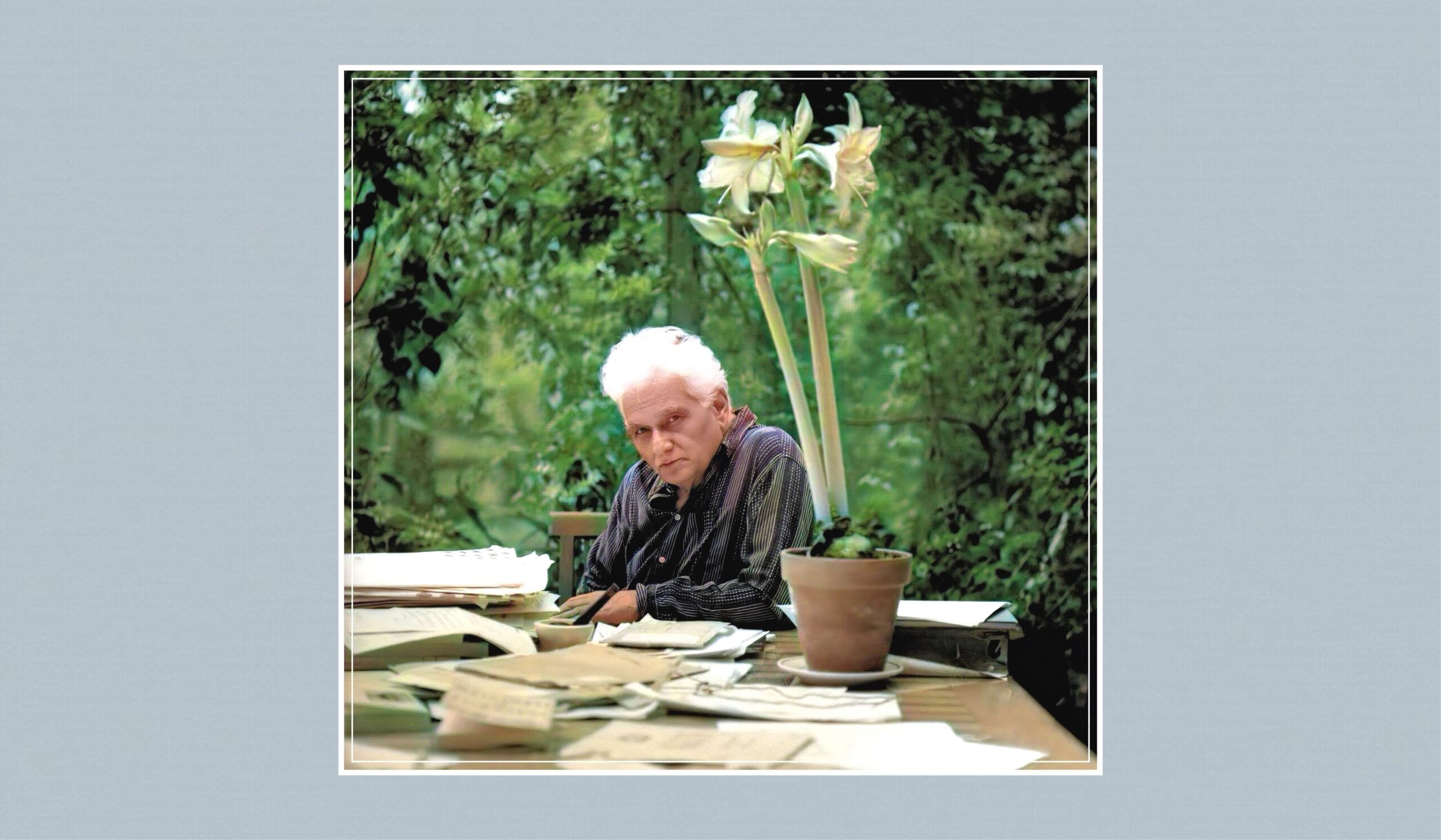











Berikan komentar