Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi maupun transmisi linguistik, namun juga dapat menjadi kapital dalam mewujudkan kekuasaan. Begitulah ungkap Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991). Bahasa dapat menjadi suatu representasi kelas dan simbol kekuasaan dari identitas kultural tertentu.
Berkaitan dengan kelas, terdapat struktur di dalam bahasa. Bahasa tidak bersifat netral, namun terdapat disposisi aktif yang mengkondisikan realitas. Dalam bahasa Jawa terdapat hierarki yang mencerminkan posisi seseorang terkait dengan relasi komunikatif dalam suatu arena. Bahasa Jawa ngoko digunakan bagi seseorang dengan posisi sosial yang setara—misalnya dengan sesama teman—sedangkan bahasa Jawa krama digunakan oleh seseorang yang status sosialnya lebih rendah terhadap orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau orang tua. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembiasaan historis yang berkaitan secara langsung dengan etika dan moral di Jawa.
Keragaman suatu bahasa dengan dialek yang menyertainya selalu terkait dengan konsep dari Bourdieu mengenai habitus. Dialek sendiri merupakan cara penuturan suatu bahasa dengan lekuk lidah yang khas sehingga memunculkan variasi intonasi dan gaya bicara yang merepresentasikan suatu identitas kultural tertentu. Dalam penuturan bahasa Indonesia sendiri terdapat beberapa macam dialek, salah satunya adalah dialek Jawa. Dialek Jawa memiliki atribusi yang populer, yakni dialek Jawa ngapak dan medok. Ngapak merepresentasikan identitas kultural Jawa Tengah bagian barat, sedangkan medok menunjukkan identitas kultural Jawa Tengah bagian timur hingga ke Jawa Timur.
Sebagai habitus, dialek di dalam bahasa muncul dari proses panjang yang menyejarah dan pembiasaan dari waktu ke waktu. Dalam penuturan bahasa Indonesia sendiri, dialek Jawa sering diatribusikan dengan Jawa medok. Terdapat ketidakpantasan yang dibekukan di dalam dialek Jawa terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini ditandai dengan “Jawa medok” untuk menegaskan identitas distingtif Jawa secara peyoratif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Di sisi lain, terdapat dialek yang dinilai lebih pantas terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam relasi komunikatif. Dialek yang memegang posisi otoritas yang lebih absah ini adalah dialek Jakarta.
Tentu hal ini tidak terlepas dari sejarah Jakarta. Di masa lalu, Jakarta menjadi kota dagang, wisata, pemerintahan, dan sebagainya yang memungkinkan para pendatang berkomunikasi menggunakan dialek Betawi atau Jakarta. Dialek Jakarta berasal dari bahasa Melayu yang banyak menyerap dari Tionghoa, seperti gua (saya) atau gue, lu (kamu) atau lo, ente, goceng (lima ribu rupiah), nyokap (ibu), bokap (ayah), dan lain-lain. Kemudian penggunaan dialek ini semakin mendapatkan keabsahannya ketika muncul berbagai tayangan di televisi, surat kabar populer, majalah remaja, dan novel remaja yang menggunakan bahasa Indonesia berdialek Jakarta sebagai bahasa tulis maupun percakapannya. Hal ini semakin menegaskan posisi otoritas dialek Jakarta dalam penggunaan bahasa Indonesia secara normatif-konstruktif.
Selain sebagai pusat ibu kota, Jakarta juga menjadi kiblat modernisme dengan berbagai citra kehidupan “kota” yang menjadi daya tariknya, seperti bisnis, tren, dan entertaintment. Para pejabat pemerintahan, model, artis, hingga pebisnis hidup di Kota Jakarta. Elitisme budaya kontemporer menjadi citra ideal bagi terwujudnya sebuah kehidupan dengan habitus yang prestise. Hal ini tidak terlepas dari diskursus yang diterima secara umum mengenai konsep tradisionalisme dan modernisme secara biner. Tradisionalisme yang biasa disematkan pada konsep “pedesaan” diartikan sebagai keterbelakangan, sedangkan modernisme yang biasa disematkan pada konsep “perkotaan” diartikan sebagai kemajuan.
Dalam konteks dialek, penggunaan suatu bahasa Indonesia dengan distingsi Jakarta akan memunculkan anggapan yang lucu, sok, dan kurang pantas jika digunakan oleh orang dengan dialek Jawa. Tentu anggapan seperti ini tidak muncul tanpa sebab. Bahkan banyak konten-konten, misalnya di YouTube, yang berisi tentang cara-cara berbicara dengan menghilangkan aksen daerah—dalam hal ini adalah medok. Mengapa ada klasifikasi yang tidak setara antara dialek Jakarta dan Jawa dalam penuturan bahasa Indonesia?
Bahasa dan Kuasa Simbolik
Berbeda dengan konsep kapital dari Marx yang menggunakan pendekatan ekonomi, Bourdieu melakukan tafsir ulang pada kapital yang bertitik tolak pada perspektif sosio-budaya. Kapital meliputi kapital ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Kapital ekonomi menjadi satu jenis kapital yang paling mudah untuk dikonversikan ke dalam kapital-kapital yang lain (Haryatmoko, 2016). Dalam konteks bahasa, kapital simbolik merupakan suatu upaya dalam melakukan strategi penguasaan ketika terjadi pertarungan simbolik antar agen di dalam medan.
Fondasi bagi suatu bahasa bersifat semenanya, namun selalu dibentuk oleh habitus. Di sini terjadi proses pembiasaan yang panjang hingga membentuk ragam dialek pada setiap habitus dan arena. Melalui praktik, kelompok agen dengan habitus yang prestise memiliki akses yang lebih besar daripada mereka yang dari kecil tinggal di suatu pedesaan yang kecil. Akses didapatkan dari kepemilikan modal yang relatif lebih banyak. Akses itu dapat berupa pendidikan yang mencakup pengetahuan dan lingkungan yang mendukung kehidupan modernisme.
Dalam konsep arena yang lebih general, kepemilikan modal-modal ini menciptakan realitas sosial yang membuatnya diakui. Kelompok dominan (kelompok yang memiliki kuasa simbolik) dapat mengkondisikan bentuk realitas melalui representasi simbolik yang absah, misalnya dalam penuturan bahasa Indonesia menggunakan sudut pandang kelompok dominan. Mekanisme kekuasaan di dalam bahasa, menurut Bourdieu, menghasilkan dua sintesa mengenai sistem simbolik, yakni structuring symbols dan structured symbols. Di sini bahasa menstrukturkan sekaligus distrukturkan realitas sosial yang telah dikonstruksikan kelompok dominan di dalam arena. Penggunaan bahasa Indonesia yang lebih absah pun dimiliki oleh kelompok dominan karena kekuasaan simbolik yang dimilikinya. Kekuasaan simbolik ini membentuk suatu diskursus mengenai norma ideal bagi dialek yang legitim dalam penggunaan bahasa Indonesia.
Kekerasan Simbolik melalui Bahasa
Melalui strategi kekuasaan simbolik, bahasa dengan dialek yang legitim dioposisikan dengan dialek daerah. Hal ini dikarenakan sebuah penguasaan membutuhkan keterlibatan dari kelompok yang terdominasi. Dalam sejarahnya yang panjang, Jakarta berhasil mendapatkan pengakuan untuk menempati posisi yang prestise secara sosial. Di sini dialek Jakarta menjadi norma ideal bagi dialek-dialek lain dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai afirmasi superioritas dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Istilah doxa dimunculkan oleh Bourdieu untuk menggambarkan situasi berupa persetujuan dari kelompok terdominasi untuk mematuhi hukum-hukum yang diciptakan oleh kelompok dominan.
Selain sebagai upaya dalam meraih atau mewujudkan kekuasaan, Bourdieu juga mengungkapkan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai instrumen dominasi (Bourdieu, 2020a). Dominasi terjadi dalam ranah simbolik, artinya, tidak terdapat kepatuhan yang berasal dari paksaan kelompok dominan. Dominasi simbolik terjadi dengan penanaman ideologi dominan yang berimplikasi pada penerimaan dari kelompok yang terdominasi. Dengan demikian, dominasi yang terjadi dinormalisasikan karena anggapan bahwa kuasa yang dimiliki oleh kelompok dominan adalah sesuatu yang absah dan terberi.
Anggapan yang lucu, kurang pantas, dan sok ketika menggunakan bahasa Indonesia non-formal dengan distingsi Jakarta bagi orang berdialek Jawa adalah sebagian konsekuensi dari perwujudan kekuasaan simbolik. Perwujudan kekuasaan ini terjadi ketika terdapat pihak yang tunduk terhadap aturan-aturan sosial yang dikonstruksikan dan diterima secara umum mengakui pihak lain (kelompok dominan/kelompok berdialek Jakarta) sebagai yang berhak untuk melakukannya.
Selain itu, bahasa menjadi representasi kelas dan selera. Bourdieu mengungkapkan bahwa, “agar ada selera, maka harus ada barang atau hal-hal yang dikelas-kelaskan” (Bourdieu, 2020b). Bahasa dengan dialek tertentu akan memunculkan citra prestise secara sosial yang menunjukkan seseorang berasal dari kelas, kelompok, dan kebiasaan tertentu. Di sini dialek Jakarta menjadi dialek yang legitim terkait penggunaan bahasa Indonesia yang pantas dengan menempatkan dialek daerah, khususnya Jawa, berada di bawahnya secara biner. Strategi dominasi ini dilanggengkan dengan menciptakan kelompok yang inferior, yaitu kelompok dengan dialek Jawa yang diatribusikan sebagai Jawa medok.
Konsekuensi dari dominasi simbolik ini adalah dengan banyaknya orang-orang daerah, khususnya Jawa, yang memaksa “lidah Jawa” mereka untuk membuatnya terdengar lebih pantas ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini karena terdapat standar ideal yang ditetapkan sebagai sesuatu yang absah melalui diskursus yang menyejarah. Selain itu, munculnya perasaan yang malu dan inferior pada kelompok yang terdominasi (kelompok berdialek Jawa) ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jawa adalah keberhasilan mekanisme dominasi simbolik yang beroperasi melalui pembiasaan.
Referensi
Bourdieu, P. (2020a). Bahasa dan Kekuasaan Simbolik (S. A. Herniwarko, Penerj.). IRCiSoD.
Bourdieu, P. (2020b). Pertanyaan-Pertanyaan Sosiologi (S. A. Herwinarko, Penerj.). IRCiSoD.
Haryatmoko. (2016). Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. PT Kanisius.

Rizki Muhammad Iqbal
Mahasiswa Sosiologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

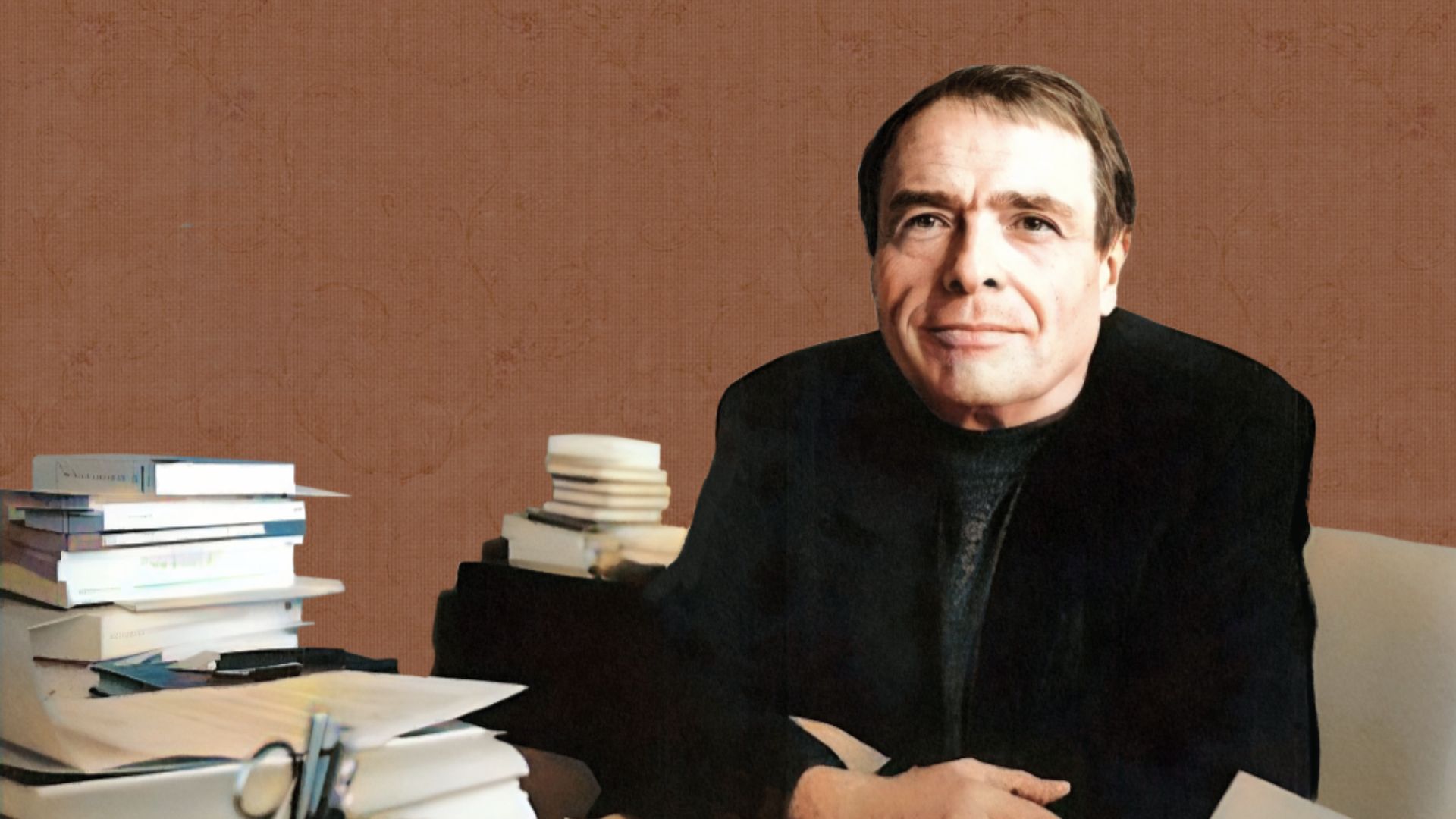








Berikan komentar