Kompleksitas hidup tidak memungkinkan manusia untuk mampu memahami segalanya. Manusia dalam dirinya sendiri adalah terbatas. Namun, sedari awal, manusia sudah mempunyai usaha untuk memahami sesuatu baik realitas yang ada dalam dirinya, maupun realitas di luar dirinya. Usaha manusia untuk mengerti sesuatu seolah menjadi kodratnya. Persoalan ini tidak luput dari pemikiran para filsuf yang memandang penting arti usaha manusia untuk ‘memahami’, ‘mengerti’, atau juga ‘menafsirkan’ sesuatu. Studi dan ilmu tentang ini disebut hermeneutika.
Schleiermacher dan Dilthey adalah dua orang yang dapat dikatakan merupakan inisiator hermeneutika secara formal. Lebih-lebih Schleiermacher, ia menggunakan hermeneutika sebagai sarana mencapai kebenaran objektif. Pandangan dan pemikiran mereka berpengaruh pada para pemikir sesudahnya. Dalam pandangan hermeneutik mereka, mereka menekankan usaha pemahaman terhadap konteks asali suatu teks atau realitas. Hermeneutika mereka memproduksi makna yang ada di masa lampau, sehingga disebut hermeneutika reproduktif. Sementara itu, tokoh yang akan saya bahas adalah seorang filsuf besar dan seorang pemikir hermeneutika. Cukup berbeda dari pendahulunya, ia meninggalkan hermeneutika reproduktif. Ia menawarkan perspektif baru dalam dan proses memahami sesuatu. Dialah Martin Heidegger.
Mengenal Martin Heidegger
Martin Heidegger lahir di Meßkirch, wilayah Schwaben, Jerman, pada tanggal 26 September 1889. Heidegger dilahirkan dan dibesarkan secara Katolik oleh ayahnya, Friedrich Heidegger dan ibunya, Johanna Kempf. Ia mengenyam pendidikan menengah di seminari. Bahkan ia pernah diterima di Novisiat Yesuit di Tisis, tetapi hanya bertahan dua tahun karena gangguan jantung. Di masa SMA ia banyak membaca buku Franz Brentano, seorang filsuf abad pertengahan yang mempopulerkan intensionalitas. Dari situlah, semangat Heidegger untuk terus mencari makna Ada tak pernah berhenti.
Heidegger memang seorang filsuf yang kontroversial. Ada setidaknya tiga skandal yang mewarnai perjalanan hidupnya. Pertama ialah keputusannya untuk keluar dari Gereja Katolik. Tidak hanya menyatakan diri keluar, ia juga mulai mengkritik Katolisisme secara tajam. Baginya, filsafat dan teologi tidak pernah dapat dipertemukan. Skandal kedua ialah keterlibatannya dalam Nazi. Heidegger disebut pernah menyatakan diri sebagai anggota dan sekaligus propagandis Nazi di Leipzig, Hiedelberg, dan Tubingen. Pidato pengukuhan rektoratnya di Universitas Freiburg juga sarat bermuatan politis dari analisisnya terhadap Dasein yang dikembangkannya dalam Sein und Zeit. Kemudian, kontroversinya yang cukup terkenal adalah perselingkuhan Heidegger dengan muridnya sendiri, Hannah Arendt.
Setelah meninggalkan jalan panggilan imamat, Heidegger melanjutkan studi filsafat. Secara mendalam, Heidegger mulai mempelajar fenomenologi yang menjadi tren ilmiah berbagai universitas di Jerman. Ia pun menekuni ajaran dan tulisan-tulisan dari Edmund Husserl yang mempelopori fenomenologi. Fenomenologi adalah metode yang ia gunakan dalam menulis bukunya, Sein und Zeit.
Sein und Zeit (1927), bisa dikatakan, merupakan opus magna dari Martin Heideggger. Di sana ia mengungkap penelusuran akan makna asali Sang Ada dalam kaitannya dengan waktu. Buku ini memuat konsep dasar yang mencerminkan pengalaman fundamental manusia, ialah kecemasan, kekhawatiran-kepedulian, dan kengerian. Nuansa tulisannya memang tidak lepas dari konteks politis dan historis di Eropa, di mana masih diliputi ketegangan perang dunia.
Dalam Ada dan Waktu ini, secara implisit, hermeneutika menjadi bahasan. Filsafat hermeneutik Heidegger memang meneruskan hermeneutika yang dirintis Schleiermacher dan Dilthey, tetapi sikapnya lebih bersifat eksentris, karena sekalipun sepaham dalam menghadapi postitivisme dan idealisme, ia menolak digolongkan dalam program hermeneutik.[1] Secara lebih jelas, konsep hermeneutika Heidegger dapat ditelusuri lewat rangkaian-rangkaian kuliahnya yang berjudul ‘Ontologie – Hermeneutik der Fakzitat’ dan juga dalam Grandprobleme der Phenomenologie.
Heidegger merupakan seorang penulis yang produktif. Selain Sein und Zeit, ia banyak menulis risalah filsafat terutama berkenaan dengan metafisika, seperti, Kant und das Problem der Metaphysik (Kant dan Masalah Metafisika-), Wast is Metaphysik? (Apa itu Metafisika?), Was heißt Danken? (Apa itu Berpikir?) dan makalah seminar dan kuliahnya yang lain. Karya filosofis dan intelektual Heidegger, tidak dapat dipungkiri, mempengaruhi pemikir besar sesudahnya seperti Hannah Arendt, Leo Strauss, Karl Lowith, Gerhard Kruger, Hans Jonas, Hans-George Gadamer, Jacques Derrida dan Michael Foucault. Masa tua Heidegger dihabiskan di pondok miliknya di Todtnauberg. Martin Heidegger meninggal pada tanggal 26 Mei 1976 di Freiburg. Ia dimakamkan dua hari kemudian di tanah kelahirannya, Meßkirch.
Hermeneutika Faktisitas – Latar Belakang Intelektual: Fenomenologi
Pendasaran filosofis karya Heidegger tidak bisa dilepaskan dari metode fenomenologi. Titik tolak Heidegger berbeda dengan Schleimacher yang di latarbelakangi romantisme Jerman atau Dilthey yang berpijak pada Lebensphilosophile. Fenomenologi adalah studi tentang fenomen. Sesuai dengan semboyan yang diusung, Zuruck zu den Sachen Selbst (kembali pada hal-hal itu sendiri), metode ini hendak melihat suatu fenomen apa adanya, sebelum segala ilmu dan pengetahuan mengatakan sesuatu tentang hal tersebut.
Heidegger mengurai fenomenologi berdasarkan dasar etimologisnya. Fenomenologi berasal dari padanan dua kata Yunani phainesthai yang berarti ‘menampakkan diri’ dan juga logos yang artinya ‘diskursus’. Fenomenologi, dengan demikian, adalah suatu diskursus tentang hal-hal yang menampakkan diri. Agar memahami apa yang menampakkan diri itu, seseorang perlu untuk menginterpretasinya. Maka, fenomenologi juga adalah suatu hermeneutika. Heidegger pun mengatakan “fenomenologi wujud manusia adalah suatu hermeneutika di dalam arti asali dari kata tersebut, manakala ia menunjuk aktivitas menafsirkan.”[2]
Hermeneutika Faktisitas
Hermeneutika Heidegger berbeda dari dengan hermeneutika pendahulunya, seperti Schleiermacher dan Dilthey. Hermeneutika Heidegger ialah melakukan penafsiran dengan membiarkan realitas itu menampakkan diri. Penafsir tidak menaruh kerangka berpikir miliknya ke dalam sesuatu yang menampakkan diri itu. Hermeneutika Heidegger tidak bersifat kognitif, menlainkan pra-reflektif. Sebab, bila penafsir menggunakan interpretasi yang selama ini ia ketahui pada sesuatu tersebut, maka tafsirannya adalah berupa pantulan pengetahuan dan realitas. Sementara, hermeneutika Heidegger benar-benar hanya membiarkan fenomen itu tampil apa adanya. Penafsir menyilahkan fenomen menyingkapkan diri apa adanya.
Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana cara memahami Ada. Letak permasalahan ini ialah bahwa Ada bukanlah fenomen. Ada merupakan keumuman dari mengada-mengada itu sendiri. Dengan demikian, Ada tidak bisa dimengerti oleh pandangan tradiosional fenomenologi Husserl yakni dualitas subjek dan objek. Sebelum ada subjek dan objek, tidak ada yang diartikulasikan dan diketahui. Inilah keadaan primordial, di mana fenomenologi tentang Ada berfungsi.
Hal yang harus disadari ialah hanya manusia yang bisa menanyakan dan mempersoalkan Ada. Mahkluk lain tentu tidak. Manusia adalah prioritas ontologis yang adalah eksistensi. Heidegger mengatakan dalam bukunya Die Technik und die Kehre, ‘Hakikat Ada membutuhkan hakikat manusia’[3]. Tanpa manusia, mustahil ada ontologi dan juga hermeneutika. Namun, pada poin ini, Heidegger menggunakan bahasa baru nan khas dalam menyebut manusia. Ia menggunakan istilah baru agar kita lepas dari konsep manusia yang diajarkan atau dirumuskan oleh teologi, filsafat, ilmu sosial, antropologi dan lain sebagainya. Istilah itu ialah Dasein. Kata Jerman ini berarti ‘ada-di-sana’. Penggunaan kata ini akan menghapus kemenduaan abstraksi subjek-objek. Dasein, bagi Heidegger ada-begitu-saja. Selain dasein, Heidegger itu menyebut manusia sebagai Sein-zum-tode (ada-menuju-kematian).
Heidegger menyebut fenomena ini sebagai keterlemparan (Geworfenheit), ‘berada begitu saja’. Dasein mengungkapkan keunikan dan kekhasan manusia yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena ‘berada begitu saja’, manusia tidak tahu tujuan dan asal hidupnya. Kenyataan bahwa Dasein hidup di dunia ini (terlempar) atau sein-zum-tode secara niscaya disebut faktisitas. (Jer: Faktizität). Heidegger menjelaskan:
The concept of ‘facticity’ implies that an entity ‘within-the-world’ has Being-in-the-world in such a way that it can understand itself as bound up in its ‘destiny’ with the Being of those entitles which it encounters within its own world.[4]
Penyatuan hermeneutika dengan faktisitas bukan berarti bahwa faktisitas menjadi objek pemahaman atau penafsiran. Faktisitas bukanlah teks, artefak, atau dokumen historis, melainkan kenyataan eksistensial manusia sebagai dasein.[5] Drama eksistensial dasein yang terlempar ke dunia menimbulkan ‘kecemasan’ (Angst). Dasein tidak tinggal diam dalam situasi ini. Ia ingin memahami ‘keterlemparannya’. Momen di mana ada pemahaman pra-reflektif terhadap keseluruhan adanya disebut Verstehen (Memahami).
Dengan demikian, memahami (Verstehen) itulah kenyataan yang ditafsirkan, Di sini, ‘memahami’ tidak memiliki objek ini dan itu tetapi cara primordial Ada menampakkan diri. Verstehen adalah cara dasein bereksistensi.[6] Budi Hardiman menjelaskan lagi. Interpretasi dalam bahasa Jerman adalah Auslegung yang diartikan oleh Heidegger sebagai ‘membiarkan terbuka’. Jika demikian, makna bukan sesuatu yang ada dalam kesadaran penafsir, melainkan berada di sana, di dalam hal itu sendiri yang menyingkapkan diri kepada penafsir. [7]
Konsep Utama: Pre-Struktur Hermeneutis
Bila dibandingkan, verstehen Heidegger lebih bercorak ontologis sedangkan verstehen Schleiermacher dan Dilthey lebih epistemologis. Sebab, Schleimacher dan Dilthey menganggap ‘memahami’ sebagai kegiatan kognitif belaka. Sementara itu, Heidegger menekankan peran pra-kognitif kegiatan ‘memahami; sebagai modus eksistensi dasein. ‘Memahami’ bukanlah aktivitas mengetahui, melainkan keterbukaan dasein terhadap dunia. Dalam pemikiran Heidegger, situasi keterlemparan membuat manusia tidak mengenal asal dan tujuannya. Maka, dasein terbuka pada berbagai kemungkinan yang akan ia hadapi. Heidegger menyebut dasein juga sebahai kemungkinan (Seinkonnen). Heidegger menulis, ‘Understanding is the existensial Being of Dasein’s own potentiality-for-Being; and it is so in such a way thar this Being discloses in itself what its Being is capable’.[8] Dengan kata lain, Palmer mengatakan, memahami adalah ‘kemampuan seseorang untuk menangkap kemungkinan-kemungkinan eksistensialnya untuk berada.’[9]
Memahami, bagi Heidegger, berciri primordial. Artinya, ia mendahului dan memungkinkan segala sesuatu bentuk pemahaman empiris. Berciri primordial memaksudkan suatu proses awali yang bekerja dalam ranah ontologis, tidak terkatakan atau terkonsep secara kognitif, tetapi mendasar secara eksistensial. Hal ini berbeda dengan cara kerja dalam ranah empiris yang mengedepankan refleksi kognisi dan indrawi manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai makna, pengalaman empiris tidak cukup. Keseluruhan relasi-relasi atau cara berada kita di dunia menentukan pemahaman kita tanpa suatu kesadaran yang mendahului.[10]
Di sinilah kontribusi Martin Heidegger. Ia mengajukan adanya konsep Vorstruktur des Verstehen (prastruktur memahami). Proses interpretasi tidak pernah berlangsung tanpa prepemahaman ini. Pra-pemahaman atau presuposisi ini terbentuk dari Bewandtnisganzheit (struktur hubungan) yaitu totalitas partisipasi seseorang pada hidupnya.[11] Totalitas ini bersifat diam, non-verbal, pra-predikatif karena berada di ranah ontologis.
Sebagai contoh, ketika seorang pujangga menggubah sebuah syair. Ia tidak sekadar memasukkan bahasa puisinya dengan pengetahuan dan perbendaharaan kata. Seorang penyair yang mencipta puisi melibatkan seluruh totalitas dirinya, baik emosi, disposisi, intelegensi, atau mungkin sisi rohaninya. Kemampuan ia berkarya sastra itulah cara beradanya. Hal tersebut mendahului segala pengetahuan intelektual tentang kata atau bait puisinya.
Verstehen dalam pengertian Heidegger sebagai modus berada merupakan suatu faktisitas. Kegiatan ini melibatkan keseluruhan cara hidup seseorang. Kemampuan dan pemahaman kognitif digerakkan oleh suatu pra-struktur pemahaman yang tidak disadari. Dalam pengertian ini pemahaman sesorang yang sebenarnya (aktual) mengandung suatu konsep pra-pemahaman. Gambar[12] di bawah ini hendak menunjukkan secara sederhana skema Verstehen menurut Heidegger.

Keterarahan Futuristik dan Interpretasi
Sifat hermeneutika Heidegger adalah kemewaktuan. Berbeda dengan Dilthey dan Schleiermacher yang mencoba menangkap makna masa silam, hermeneutika Heidegger selalu memiliki keterarahan ke masa depan. Sebab, sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya, Dasein selalu memiliki posibilitas eksistensial. Palmer mengatakan bahwa ‘keseluruhan pemahaman bersifat temporal, intensional dan historis.’[13] Masa lalu adalah sejarah, masa kini yang seseorang itu sedang alami, tetapi masa depan adalah misteri. Itu artinya masa depan merupakan kemungkinan-kemungkinan. Maka proses memahami dalam hermeneutika Heidegger erat kaitannya dengan Entwurf (proyeksi) terhadap masa depan.
Hermeneutika tidak lepas juga dari suatu interpretasi. Sebelumnya, kebanyakan orang memahami bahwa pemahaman diperoleh dengan suatu interpretasi. Artinya, interpretasi mendahului suatu pemahaman. Namun, hal ini tidak sama halnya dengan pemikiran Heidegger. Pemahaman datang lebih dulu daripada interpretasi. Heidegger mengatakan bahwa interpretasi adalah proyeksi yang dimulai dari pra-struktur memahami. Oleh karena memahami dimengerti sebagai cara berkesistensi, maka interpretasi, bagi Heidegger hanyalah pengembangan dari kegiatan memahami.
Heidegger mengusung tiga terminologi kegiatan interpretasi, yakni Vorhabe, Vorsicht, dan Vorgriff. Vorhabe secara harfiah berarti ‘rencana’ tetapi diartikan sebagai ‘memiliki lebih dahulu’. Hal ini berarti penafsir memiliki pemahaman umum terhadap sesuatu secara a priori. Lalu, Vorsich berarti ‘melihat lebih dulu’. Istilah ini memaksudkan proyeksi makna bagi masa depan. Sementara itu, Vorgriff berarti ‘menangkap lebih dahulu’ dengan suatu konsep dengan arah masa depan.
Relevansi: Pancasila sebagai Modus Eksistensi Bangsa Indonesia
Budi Hardiman mengatakan, Heidegger memberi kritik atas hermeneutika reproduktif para pendahulunya, yang mana mereka mencoba menggali makna hermeneutis dari situasi asali masa silam suatu teks. Ada dua kritik Heidegger:[14]
- Adalah mustahil mereproduksi makna dari masa silam, sebab dasein adalah keterbukaan atas kemungkinan-kemungkinan. Itu berarti mengandaikan adanya proyeksi makna ke masa depan. Karena objek interpretasi bukanlah upaya untuk menampilkan sesuatu yang lampau pada masa kini melainkan sesuatu untuk disingkap dengan mengantisipasi maknanya.
- Oleh karena itu, hasil interpretasi tidak pernah tunggal. Kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bersifat jamak. Tidak ada standar kebenaran objektif yang tunggal dalam interpretasi.
‘Memahami’ sebagai cara bereksistensi hendak saya kontekstualisasikan dengan situasi Indonesia. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Dasar negara ini merupakan konsensus the founding fathers Indonesia sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya, termuat lima dasar peri kehidupan bangsa Indonesia. Ada lima nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Dengan pendasaran hermeneutika Heidegger, ‘memahami’ Pancasila kini bukan sekadar pengetahuan reflektif atau pergulatan ranah pikiran saja, tetapi menyangkut pra-reflektif yang artinya bersifat eksistensial bagi bangsa Indonesia. Kecenderungan positivistik dalam memahami Pancasila menjadikannya seolah pisau bermata dua. Di satu sisi Pancasila hanya sekadar semboyan atau dasar negara yang harus dihafal dan dilafalkan ketika upacara nasional. Di sisi lain, makna Pancasila dikerdilkan karena memuat kepentingan ideologis kelompok tertentu.
Akhir-akhir ini begitu banyak kisah dan berita tentang penolakan Pancasila sebagai dasar negara. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia justru secara aneh ‘menyerang’ Pancasila. Saya katakan aneh, sebab Pancasila adalah dasar ontologis bagi bangsa Indonesia. Valentinus Saeng menyebut:
Kelima asas merupakan roh eksistensial manusia dan bangsa Indonesia sebagai bagian dari realitas historis ada. Indonesia dan sejarah hidupnya merupakan salah satu perwujudan ada dalam ruang dan waktu tertentu. Karena itu, dasar ontologis Pancasila adalah realitas Indonesia baik sebagai pribadi maupun bangsa yang menjadi bagian integral dari realitas semesta dan umat manusia.[15]
Pancasila sebagai dasar negara yang menggambarkan kepribadian bangsa tidaklah milik dan menjadi monopoli orang-orang tertentu. Pancasila sebagai cara berada bangsa, terbuka kemungkinan-kemungkinan (Seinkonnen) untuk diinterpretasi oleh siapapun tanpa pakasan, hasutan, bahkan yang pernah terjadi: alat hegemoni penguasa. Atas alasan ini, kalimat yang menyebut Pancasila adalah final tidaklah benar. Final sebagai dasar negara yang tidak mampu diganggugugat itu benar tapi tidak atas ketertutupan interpretasi. Pancasila memiliki keterarahan ke masa depan, dalam hal ini adalah proyeksi ke masa depan bangsa. Sehingga segala usaha untuk kembali mereproduksi Pancasila seturut pengertian lampau adalah absurd.
Drama eksistensial Dasein, oleh Heidegger, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa proses memahami adalah sebagai cara bereksistensi. Inipun mengandaikan adanya pra-struktur memahami, bukan sekadar proses mental atau kognitif belaka. Pancasila pun demikian halnya. Ia menjadi modus eksistensi bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia, hendaknya dengan mantap, meminjam kata Armada Riyanto, berseru ‘Áku Indonesia, Aku Pancasila!’
Daftar Pustaka
Hardiman, F. Budi (2003). Heidegger dan Mistik Kesadaran. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Hardiman, F. Budi (2015). Seni Memahami: Hermeneutika dari Schlemaicher sampai Derrida. Yogyakarta: Kanisius.
Hardiman, F. Budi (2018). ‘Heidegger di Zaman Telepon Genggam’, Basis, No. 07-08.
Heidegger, Martin (1962). Being and Time, (Judul Asli: Sein und Zeit)Penerjemah. John Macquarrie dan Edward Robinson. Oxford: Blackwell Publishers.
Palmer, Robert E. (2003). Hermeneutika: Teori Baru tentang Interpretasi (Judul Asli: Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer), Penerjemah. Mansur Hery dan Damanhuri Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poespoprodjo, Wasito (2004). Hermeneutika. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.
Saeng, Valentinus, (2017). Diktat-Hakikat Pancasila: Pancasila sebagai Filsafat. Malang: STFTWS.
Wibowo, A. Setyo (2018). ‘Kronologi Jalan Hidup
Heidegger’, Basis. No. 07-08.
[1] Hardiman, F. Budi (2015). Seni Memahami Hermeneutika dari Schlemaicher sampai Derrida. Yogyakarta: Kanisius, 99.
[2] Heidegger, Martin (1962). Being and Time. (Judul Asli: Sein und Zeit)Penerjemah. John Macquarrie dan Edward Robinson. Oxford: Blackwell Publishers, 62.
[3] Poespoprodjo, Wasito (2004). Hermeneutika. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 74.
[4] Martin Heidegger, 82.
[5] Budi Hardiman, 107.
[6] Ibid., 107.
[7] Ibid., 107.
[8] Heidegger, 184.
[9] Palmer, Robert E. (2003). Hermeneutika: Teori Baru tentang Interpretasi (Judul Asli: Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer), Penerjemah. Mansur Hery dan Damanhuri Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 159.
[10] Hardiman, 114.
[11] Ibid., 114.
[12] Penggambaran secara lain dari gambar pada buku Seni Memahami hlm. 116.
[13] Palmer , 162.
[14] Hardiman, 126
[15] Saeng, Valentinus, (2017). Diktat-Hakikat Pancasila: Pancasila sebagai Filsafat. Malang: STFTWS, 3.

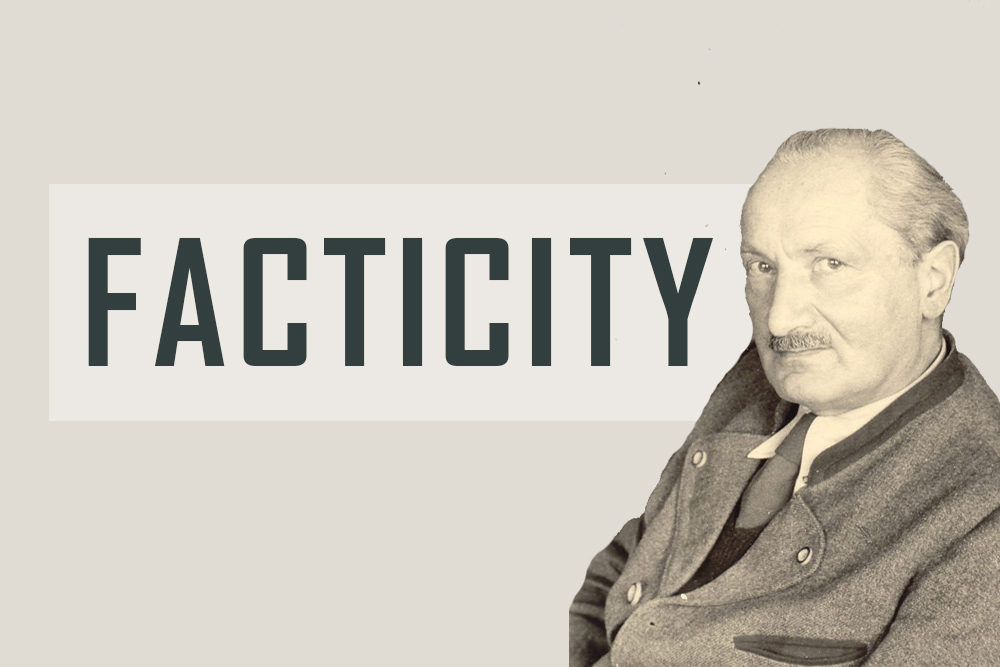







Berikan komentar