Karya seni berlatar Marxisme seringkali dipandang kaku secara bentuk dan artistik. Karena seni yang-Marxis adalah seni yang-politis, dan karenanya dituntut untuk selalu berkiblat pada isi dan maksud tertentu, kebaruan bentuk dan artistik menjadi terpinggirkan. Sebab, isi hanya bisa tersampaikan secara utuh apabila bentuk tunduk secara penuh kepadanya. Tak berhenti di situ, Marxisme juga dianggap gagal dalam mengimajinasikan kesenian. Para seniman formalisme Uni Soviet di era Stalin, misalnya, disingkirkan dan estetika realisme sosialis menjadi satu-satunya kiblat sah yang sesuai garis partai. Pada akhirnya, seni yang dilatari Marxisme adalah seni yang monoton dan begitu-begitu saja. Ia revolusioner dari segi isi, tetapi prematur dari segi bentuk.
Di sisi lain, bentuk di dalam sejarah seni terus berjalan secara dialektis. Pada 1889, komponis Prancis, Claude Debussy, untuk pertama kalinya terpukau menyaksikan penampilan sekelompok kecil pengrawit gamelan di hajatan Paris Exposition Universelle. Pada tahun 1900, dalam hajatan yang sama, ia melihat karawitan dimainkan dengan format ansambel utuh. Pengalaman Debussy mencicipi bebunyian logam dari Nusantara itu kemudian menginspirasinya untuk menciptakan karya solo piano berjudul “Pagodes” (1903).
Karya-karya Debussy kemudian dianggap oleh para sejarawan sebagai pintu masuk musik menuju masa modern. Fenomena artistik serupa juga terjadi di bidang seni lainnya sepanjang dekade-dekade peralihan abad itu. Setelahnya, dialektika bentuk antara klasik dan tradisi, antara seni dan teknologi, atau antara barat dan timur, menjadi pemandangan yang lumrah dijumpai. Lalu, bagaimana Marxisme menjawab perkembangan bentuk artistik yang menyejarah itu?
Sebagai suatu sejarah pemikiran, estetika Marxis sebetulnya memiliki cara pandang yang amat beragam dalam memandang seni, termasuk juga dalam menimbang bentuk sebagai wahana bermain seniman. Karena itu, saya tertarik untuk meninjau kembali bentuk sebagai aspek yang juga dikaji secara mendalam oleh para estetikawan Marxis, dan pada gejala tertentu, juga oleh para senimannya.
Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan lahirnya estetika Marxis dengan melihat pemikiran Karl Marx sendiri dalam memandang seni. Lalu, penulis akan mengulas secara ringkas para pemikir estetika Marxis di Soviet dan Barat. Di sini saya akan lebih berfokus pada pemikiran yang secara spesifik mengartikulasikan bentuk daripada isi. Sebab, eksplorasi bentuk memang punya dilemanya sendiri, yang seringkali menjadi sasaran empuk dalam kritik terhadap pemikiran Marxis di wilayah estetika dan seni. Estetika Marxis sebagai metode membaca dan mencipta karya seni dalam situasi kontemporer bakal menjadi sajian penutupnya
Lahirnya Estetika Marxis
Pemikiran estetika Marxis sendiri tidak dapat dijangkarkan pada pemikiran Karl Marx secara utuh. Pemikirannya mengenai seni dan estetika tersebar dalam sedikit kepingan-kepingan kecil di antara banyak tulisannya. Meski begitu, secara keilmuan, seni bukanlah sesuatu yang asing bagi Marx. Sepanjang masa-masa kuliah filsafat dan hukumnya, antara tahun 1835-1841, ia secara ketat mempelajari sejarah sastra dan estetika klasik Jerman. Ia bahkan menghadiri kuliah-kuliah mengenai kesusastraan kuno, mitologi kuno, dan seni modern (Lifshitz, 1973: 12).
Selain itu, pada tahun 1837, masa-masa transisinya menjadi seorang Hegelian, Marx juga secara tekun bergelut mempelajari estetika Hegel. Lebih jauh, ketertarikan Marx muda terhadap seni tidak hanya terbatas pada dimensi teori belaka. Pada masa yang sama, ia telah menulis puluhan puisi, satu babak drama fantasi, dan sebuah novel fiksi komedi berjudul Scorpion and Felix, yang tidak pernah ia terbitkan selama masa hidupnya.
Puisi dan prosa yang Marx muda hasilkan, tentu ini sudah bisa ditebak, jauh dari kesan agitatif. Alih-alih menyerukan perlawanan lewat tulisan-tulisannya, Marx condong bermain-main dengan bentuk khas estetika romantik yang mengemuka saat itu. Maka kita akan menemui frasa-frasa semacam “air menderu serupa hantu” atau “mereguk sungai laut sampai kesat” atau “binarnya kerling mata jeli” dalam puisi-puisi liris Marx yang disadur oleh Yovantra.
Pada masa selanjutnya, paradigma Marx terhadap seni mulai bergeser, terutama saat ia memposisikan dirinya sebagai kritikus. Dalam buku Marxist Esthetics (1973), Henri Arvon membagi dua kecenderungan Marx dalam memandang karya seni. Pertama, Marx menitikberatkan bahwa seni haruslah melandasi dimensi teori dan praksis gerakan sosial. Dalam hal ini Arvon melihat dari dua tulisan Marx yang berkutat pada kritik sastra. Adalah karya Marx berjudul The Holy Family (1845) yang memuat komentarnya mengenai novel berjudul “Mysteries of Paris” (1842) karya penulis Eugene Sue, dan dokumen korespondensinya dengan Ferdinand Lassalle, yang membahas mengenai naskah drama berjudul “Franz von Sickingen” (1859) gubahan Lasalle sendiri.
Ringkasnya, perhatian Marx dari dua tulisan itu tertuju pada relasi antara seni dan fungsi sosialnya. Ia, misalnya, mencela karya Sue karena tidak melancarkan kritik kepada masyarakat kapitalis di Paris. Lalu, dalam kritiknya terhadap drama Lasalle, Marx mengatakan drama itu dapat membikin orang percaya bahwa kekalahan dari gerakan sosial apapun tak dapat dihindari karena revolusi sendiri secara internal mengandung cacat fatal.
Pada poin kedua, Arvon melihat Marx sebagai orang yang juga mengagumi para penulis yang berkutat pada eksplorasi bentuk dan artistik. Artinya, Marx sendiri memberi ruang apresiasi kepada aspek bentuk sebagai elemen penting yang menampak di dalam karya. Menurut Arvon, Marx terutama sekali menghargai gaya seperti yang terkandung dalam karya para penulis lampau seperti Aiskhilos, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Walter Scott, dan Honoré de Balzac.
Kendati begitu, penilaian Marx terhadap seniman-seniman kontemporer di masanya tetap ditentukan oleh bagaimana sikap politik para seniman tersebut. Karena itulah Marx mengapresiasi, misalnya, karya-karya dari penyair seperti Ferdinand Freiligrath dan Georg Herwegh, yang tidak memiliki kemapanan artistik, tetapi punya sikap politik yang jelas dalam perjuangan kelas (Arvon, 1973: 2-4).
Pada dasarnya, menurut Arvon, Marx memandang bahwa seni sesungguhnya tak dapat menghindar dari konteks sosio-historis. Sebuah karya seni, dengan demikian, haruslah ditafsir sebagai produk sejarah yang terus hadir berulang dan berubah tanpa henti. Argumen itu didasari pada pemikiran materialisme historis Marx. Karena itu, dalam cakrawala Marxis, idealisme yang menganggap bahwa seni memiliki fenomena keindahan dan nilai estetis yang abadi, cenderung melihat seni sebagai produk yang terisolasi dari sejarah, yang seolah-olah hadir dari ruang hampa dan menganulir evolusi sejarah sebagai ilmu. Maka, kondisi material yang mensituasikan sebuah karya dan senimannya adalah tolok ukur terpenting. Sebab, bukan kesadaran individual seniman yang menentukan lahirnya sebuah karya, melainkan kesadaran yang diselubungi keadaan sosial mereka.
Meski begitu, pemikiran estetika Marxis yang ada saat ini tak lain merupakan suatu sejarah pemikiran, hasil dari pembacaan tiap-tiap tokoh terhadap karya-karya Marx dan situasi kenyataan yang mereka alami. Kita, misalnya, akan menemui corak pemikiran yang berbeda antara para birokrat Uni Soviet dan para pemikir Marxisme Barat dalam memandang seni. Tegangan antara isi dan bentuk, antara realisme dan formalisme, menjadi panorama utamanya. Saya akan membahasnya lebih lanjut.
Secuplik Dinamika di Soviet
Dari dilema yang ditinggalkan Marx, terutama setelah memasuki abad ke-20, tegangan antara bentuk dan isi selalu mengemuka dalam perdebatan internal estetika Marxis. Pada penerapan negara sosialis di Uni Soviet, misalnya, kita akan melihat bagaimana kebijakan birokrat kebudayaan, seperti Andrei Zhdanov, merepresi dimensi teori dan praktik gerakan seni avant-garde lewat diktum realisme sosialis yang menjadi kiblat mutlak estetika Soviet sepanjang Stalin berkuasa.
Namun, sebelum itu, para seniman dan estetikawan di Soviet juga punya pengandaian lain dalam seni. Proletkult, misalnya, adalah sebuah gerakan seni garda-depan yang dibentuk usai Revolusi Oktober 1917. Jauh dari kesan doktrin Marxisme terhadap seni yang realis dan kaku, mereka justru hendak membangun sebuah kebudayaan baru dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk artistik revolusioner dan membabat habis kebudayaan lama Kekaisaran Rusia. Kebudayaan baru yang hendak dicapai itu disebut kebudayaan proletar.
Kecenderungan semacam itu dapat dilihat dalam karya komponis Soviet, Alexander Mosolov, berjudul “The Iron Foundry, Op. 19” misalnya. Mosolov, yang notabene seorang komponis musik klasik, menciptakan sebuah karya orkestra yang terdengar asing. Ia tidak saja menegasi idiom-idiom musik tradisi Rusia, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk memutus mata rantai para komponis Rusia terdahulu. Jika pembaca bersedia mendengar, karya Mosolov itu berbunyi seperti tumpukan raungan mesin. Bagi manusia zaman sekarang, kita barangkali tak kaget dengan bebunyian semacam itu. Tetapi fakta bahwa karya itu dibuat pada tahun 1926 adalah soal lain. Karena itulah gaya musik Mosolov, dan gaya para seniman sejenis waktu itu, disebut futurisme.
Masih soal bentuk. Pemikir Marxis di Soviet seperti Leon Trotsky pun punya pengandaian lain. Dalam esainya, Communist Policy Toward Art (1923), Trotsky mengatakan bahwa partai perlu memberi kesempatan berkembangnya seni-seni baru di Soviet. Artinya, bagi dia, seni haruslah bergelut secara internal dengan dunianya sendiri dalam rangka menjawab perkembangan sejarah seni. Sebaliknya, alih-alih mengatur, menurut Trotsky, partai seharusnya juga memberi perlindungan untuk memastikan otonomi seni berjalan secara merdeka. Di sisi lain, partai perlu memberi kredit kepada para seniman yang turut berkontribusi dalam revolusi dan berpartisipasi dalam merumuskan artikulasi artistik Uni Soviet.
Meski mendukung otonomi seni, Trotsky juga mengkritik upaya kelompok Proletkult dan seniman garda-depan lainnya yang hendak membangun apa yang mereka sebut kebudayaan proletar, yang secara ambisius menegasi kebudayaan lama sisa-sisa borjuis dan feodal. Pokok masalah yang langsung mengemuka adalah perkara waktu. Sebab, kaum proletar baru saja berhasil mengambil alih negara dan akan bergelut dalam tugas panjang untuk menjalankan transisi menuju tatanan komunisme. Trotsky mengajukan satu pertanyaan penting: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kebudayaan baru ini? Karena itu, Trotsky menawarkan jalan tengah mengenai tanggung jawab seni dalam melakukan kebaruan demi sejarahnya sendiri, alih-alih menciptakan kebudayaan yang seolah-olah terlepas dari jalannya sejarah, termasuk mencerabutkan diri dari sejarah kebudayaan borjuis dan feodal yang telah berlangsung berabad-abad di Rusia.
Pembersihan seni dari berbagai wacana revolusi bentuk artistik mulai terjadi saat kiblat estetika dimutlakkan. Pada tahun 1934, dalam pidatonya di Kongres Penulis Soviet Pertama, Zhdanov memperkenalkan realisme sosialis secara lebih utuh dan komprehensif. Ia menyebut penulis, sebagai “insinyur jiwa manusia”, punya tanggung jawab sosial untuk menggambarkan realitas setepat mungkin dalam perkembangan revolusioner kehidupan. Kebenaran dan ketepatan dari citra artistik itu, kata dia, harus sebangun dengan tugas transformasi ideologis, yakni tugas untuk mendidik rakyat pekerja dalam semangat sosialisme. Sejak pidato itu, seniman-seniman yang dinilai tidak berkomitmen secara eksplisit dan tidak mencerminkan semangat realisme sosialis pun mulai digiring ke sudut-sudut tergelap.
Apresiasi Bentuk Marxisme Barat
Dalam pemikiran Marxisme Barat, kita akan menemui banyak tokoh yang memberi ruang terhadap kebaruan bentuk dan artistik. Sosok-sosok seperti Ernst Bloch, Bertolt Brecht, dan Theodor Adorno, misalnya, menawarkan suatu corak pemikiran estetika yang sangat berbeda dari Marxisme klasik maupun Soviet. Bloch bahkan melangkah lebih jauh. Ia punya pengandaian yang lebih bersifat idealisme ketimbang materialisme. Penerapan imajinasi utopia dalam berkarya seni adalah salah satu pemikirannya.
Pemikiran Bloch itu tertuang di dalam esai-esainya yang terangkum di buku The Utopian Function of Art and Literature (1988). Bagi Bloch, seni memiliki fungsi untuk menggambarkan imajinasi tentang kehidupan yang didambakan. Pemikirannya ini terinspirasi oleh buku “Utopia” (1516) karangan penulis Inggris abad pertengahan, Thomas More. Fiksi itu mengisahkan masyarakat, lengkap dengan adat istiadat, keagamaan, sosial, dan politik yang sepenuhnya berbeda dari dunia nyata, di sebuah pulau fiktif bernama Utopia di Samudra Atlantik.
Bagi Bloch, imajinasi utopia memiliki kemungkinan untuk diwujudkan di masa depan. Utopia, dengan begitu, bukanlah tatanan yang tidak ada, melainkan tatanan yang belum ada. Terwujud atau tidaknya tatanan itu bergantung pada apakah orang percaya dengan kekuatan idealnya, yang kemudian rela bekerja untuk mewujudkannya. Dengan begitu, semakin manusia bertekad untuk menemukan Pulau Utopia itu di luasnya samudra, maka semakin ada harapan pulau itu benar-benar ditemukan di lautan.
Pengandaian Bloch barangkali serupa fiksi spekulatif yang menggambarkan suatu tatanan asing dengan berbagai konvensinya. Namun, baginya, utopia itu harus tetap dikondisikan oleh kenyataan material, yang memiliki “derajat kebenaran yang nyata” (Bloch, 1988: 15-16). Karena itu, fungsi karya seni dalam menggambarkan utopia dapat diartikan sebagai upaya seorang seniman dalam mengkonstruksikan imajinasi sebagai proyeksi masa depan manusia untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih baik: sadar secara sosial, manusiawi, dan adil. Dan sejauh Bloch adalah seorang Marxis, pengandaian utopisnya, saya kira, harus tetap dibaca sebagai imajinasi menuju tatanan yang ideal secara Marxis.
Dengan begitu, seni, dalam kacamata Bloch, tidak melulu memotret kenyataan yang tampak. Lebih dari itu, seni dapat memotret kenyataan yang diimajinasikan. Tak pelak lagi, Bloch terjebak dalam idealisme. Ia pun mengakuinya. Namun, ia mengantisipasinya dengan mengatakan bahwa idealisme sesungguhnya eksis dalam setiap titik berangkat manusia, yang juga ada dalam segala kekuatan formatif, konstruktif, dan kreatif. Hanya jika faktor-faktor itu tidak direalisasikanlah idealisme berujung pada ide murni yang tak terekspresikan, tak terkreasikan, dan tak terepresentasikan (Bloch, 1988: 112-113).
Pemikir lain, Bertolt Brecht. Sebetulnya, Brecht bukan saja seorang pemikir, tetapi juga seorang praktisi. Ia adalah seorang dramawan paling terkemuka di Eropa pada awal abad ke-20, dan punya sumbangsih penting dalam sejarah pemikiran estetika Marxis. Ia, misalnya, merehabilitasi terminologi realisme yang spesifik dan sempit sebagai satu corak artistik, menjadi term yang lebih luas dan cair.
Bagi Brecht, realisme sebagai satu corak estetika yang mengedepankan kemiripan citra dengan realitas adalah terminologi lama. Dengan berubahnya cara manusia bertahan hidup, dan karenanya berubah pula realitas yang ada, kita harus melepaskan diri dari aturan klasifikasi estetika yang terkesan abadi itu. Artinya, menurut Brecht, realisme bukan melulu suatu deskripsi (artistik) yang ajek tentang kenyataan, di mana kita bisa membaui, mencicipi, atau merasai segala sesuatu di dalam sebuah karya, melainkan harus dikonsepsikan secara luas, baik secara artistik juga politik (Brecht, 1980: 81-82).
Dengan begitu, sebuah karya lukis beraliran ekspresionisme, misalnya, tidak serta-merta dianggap sebagai formalisme semata. Karya tersebut bisa disebut realisme apabila isinya (bukan bentuk) memang mengandung cerminan realitas. Sebaliknya, karya lukis bergaya realisme justru dapat disebut sebagai formalisme sepanjang karya tersebut lebih mengedepankan aspek-aspek kecanggihan teknis, tetapi kosong dari segi isi.
Formula realisme Brecht sedikitnya dilandasi lima kunci: menunjukkan kompleksitas masyarakat; membongkar norma-norma umum kelas penguasa; berangkat dari sudut pandang kelas yang menawarkan solusi seluas-luasnya bagi kesulitan-kesulitan mendesak yang menjerat rakyat; mengutamakan unsur kebaruan; memungkinkan konkretisasi dan mengambil abstraksi darinya.
Kendati begitu, kata Brecht, formula dasar realismenya tetap dapat diperluas. Sebab, dalam berkarya, seniman sudah tentu akan melibatkan fantasi, orisinalitas, humor, dan penemuannya. Dengan membersihkan dan merumuskan ulang term realisme, Brecht membuka jalan terhadap eksplorasi bentuk tanpa harus otonom dengan isi.
Otonomi Bentuk Sebagai Perlawanan
Dari sedikit paparan di atas, anggapan bahwa seni harus didaktis hanyalah salah satu dari sedikit varian dari banyaknya variasi yang ada di dalam sejarah pemikiran estetika Marxis. Meski begitu, upaya birokratisasi seni di Soviet mestinya tetap perlu dilihat dari realitas material yang mereka hadapi, terutama gejolak perang saudara pasca-revolusi di mana tentara nasionalis Rusia ditukangi negara-negara kapitalis. Artinya, rumusan estetika yang berkiblat pada cita-cita sosialisme adalah doktrin internal Soviet untuk membersihkan individualisme borjuis. Negara-negara sosialis lain seperti Kuba, misalnya, yang baru mencapai revolusi pada 1959, memiliki realitas yang berbeda. Di sana, praksis kesenian lebih lentur dan otonom. Meski begitu, otonomi itu sebetulnya tetap bergerak dengan kesadaran tertentu.
Pada tahap ini, saya mau memberi satu contoh tentang bagaimana otonomi seni yang berlandaskan Marxisme bekerja. Adalah komponis Leo Brouwer (1939-), yang lebih menekankan eksplorasi bentuk ketimbang isi dalam merumuskan karya. Nyaris seluruh karyanya adalah musik instrumental, terutama untuk gitar klasik. Dalam komposisinya, ia mengelaborasi idiom musik tradisi Afrika-Kuba, terutama figure melodi dan ritme. Namun, ia tidak mengeksploitasi idiom tersebut menjadi sebuah komposisi barat yang ke-Kuba-Kuba-an atau sebuah komposisi tradisi yang kebarat-baratan, melainkan membangun sebuah karakter yang sepenuhnya baru.
Untuk mencapai itu, Brouwer pertama-tama menegasi sistem harmoni konvensional musik barat. Kecenderungan ini kian kentara dalam karya-karyanya sejak dekade 1970-an. Alih-alih menggunakan sistem tonalitas dan akor mayor-minor, misalnya, ia justru berangkat dari penggunaan modus-modus, ragam skala melodi yang disusun dengan interval tertentu, tanpa berjangkar pada tonalitas ajek. Pada aspek ritme, ia mengeksplorasi ritme tradisional Kuba yang kompleks, yang diwariskan dari musik-musik perkusi yang mengiringi ritus dan tarian masyarakat Afrika-Kuba. Karena itu, alih-alih meninggalkan warisan budaya lama untuk membangun budaya baru seperti yang dimaksudkan para seniman Proletkult di Soviet, Brouwer justru merangkul kekayaan budaya rakyat untuk membangun tatanan artistik baru. Dengan kata lain, ia memandang sebuah perjalanan artistik juga merupakan sebuah perjalanan sejarah manusia.
Sampai di sini, kecenderungan Brouwer yang bersifat formalistik langsung mengemuka. Namun, upayanya yang terkesan formal itu akan jelas duduk perkaranya jika dibaca sebagai upaya melawan gelagat estetika yang terus bermesraan dengan industri. Dalam sebuah wawancara, Brouwer mengatakan bahwa, melalui musiknya, ia hendak melawan klise. Klise yang ia maksud adalah penggunaan sistem tonal (sistem yang berjangkar pada nada dasar tertentu) dalam membangun sebuah komposisi.
Sistem itu, kata Brouwer, telah menjadi sajian repetitif yang digunakan oleh banyak musisi dan turut mengakomodasi banalitas. Dalam konteks musik film, misalnya, menurut Brouwer, aspek musik berfungsi untuk menggerakkan emosi terprediksi yang ditujukan untuk memainkan perasaan para penonton. Bahwa adegan sedih perlu diiringi dengan nuansa minor, adegan senang dengan nuansa mayor, adegan tegang dengan nuansa diminis, dan seterusnya. Pada tahap ini, musik di dalam film dicirikan pada aspek fungsinya. Brouwer menolak segala jenis fungsionalitas semacam ini.
Maka, kita akan segera ingat dengan apa yang telah dilakukan oleh komponis Austria, Arnold Schoenberg, pada awal abad ke-20 lalu. Bersama dua muridnya, Alban Berg dan Anton Webern, Schoenberg dikenal sebagai pendiri Aliran Wina Kedua yang mensistemasi teknik komposisi dodekafon atau teknik 12-nada sebagai usaha untuk melakukan apa yang ia sebut sebagai “emansipasi disonan”. Di dalam musik, disonan berarti kombinasi nada-nada yang menghasilkan bunyi yang kasar. Teknik komposisi 12-nada menyetarakan nada-nada kromatik dengan menegasi sifat-sifat hierarkis seperti tonika, dominan, mayor-minor, dan dengan begitu, mendobrak demarkasi antara harmoni dan disonan.
Emansipasi artistik yang dilakukan Schoenberg inilah yang mengilhami Adorno dalam melakukan kajian serius terhadap musik-musik baru. Ia menuangkan gagasannya itu di buku Philosophy of New Music (1949). Menurut Adorno, musik-musik baru patut dibela dan diperjuangkan. Sebab, musik-musik semacam itu hendak menentang dominasi pasar dan membongkar paradigma artistik lama. Untuk memahami mengapa Adorno memperjuangkan apa yang disebut sebagai “musik baru” itu, pertama-tama kita perlu memahami apa yang menjadi perhatian Adorno dalam kritiknya terhadap industri dan ideologi.
Adorno berangkat dari ratapannya terhadap kesenian di era produksi massal. Berbeda dari Walter Benjamin, pemikir Mazhab Frankfurt lainnya, yang menganggap bahwa produksi massal di wilayah kesenian membuat orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses karya seni, meski “aura” di dalam karya seni menjadi luntur karenanya, Adorno justru menganggap hal itu sebagai satu tekanan epistemologis bagi keberlangsungan seni sendiri. Baginya, para perusahaan besar di wilayah kebudayaan, seperti label rekaman musik, misalnya, justru secara tidak langsung mengendalikan musik untuk sejalan dengan statistika pasar.
Sampai di sini, Adorno menganggap industri, melalui produksi massal dan distribusinya, telah merepresi pencipta sekaligus penikmat karya. Bahwa karya berarti harus sesuai selera pasar; dan bahwa publik, yang direpresentasikan sebagai pasar, pada akhirnya justru selalu disodori “produk-produk” serupa. Karena inilah, menurut Adorno, masyarakat justru terikat pada suatu tradisi yang kaku dan rapuh (Adorno, 2006: 88).
Karena itu, bagi Adorno, otonomi seni yang mengedepankan emansipasi artistik tak lain adalah usaha untuk membebaskan diri dari semua dominasi, baik dominasi pasar maupun dominasi tradisi lama yang telah mengakar begitu kuat. Otonomi, dengan kata lain, adalah usaha menjauhkan diri dari hubungan konkret dengan semua yang hendak menguasainya. Ia lalu mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh pelukis Pablo Picasso: menentang dominasi teknologi (fotografi) sekaligus tradisi seni lukis Barat.
Situasi serupa juga mengintai para komponis di abad ke-20. Artinya, selain bergelut dengan industri dan pasar, komponis seperti Schoenberg juga menentang tradisi musik sendiri. Dengan mengutip Schoenberg, Adorno menggambarkan bahwa para pendengar musik yang terlatih pasti akan tahu ke mana sebuah musik di era romantik, misalnya, bergerak. Ini tidak mengherankan. Sebab, musik romantik bertolak dari sistem harmoni yang digerakkan oleh logika tonal. Di masa sekarang pun, kita tak akan kesulitan mengulik dan menghafal progresi akor dari sebuah lagu pop. Baik musik romantik Jerman maupun musik pop Sunda, misalnya, sebetulnya digerakkan oleh logika musik yang sama.
Jika ditelusuri lebih lanjut, pengandaian Brouwer dan pembelaan Adorno terhadap emansipasi bentuk justru bertopang pada rasionalitas isi, yakni usaha melawan banalitas dan dominasi. Di sini kita juga menemukan irisan dengan corak realisme ala Brecht: isi ternyata tetap mengandaikan bentuk, betapa pun revolusionernya bentuk yang dipresentasikan. Bentuk, dengan begitu, bukan wahyu yang jatuh dari langit, bukan pula inspirasi yang ditiupkan oleh malaikat. Presentasi artistik justru didasari pada maksud-maksud rasional yang diabstraksi dari pengalaman material.
Di sini, saya juga hendak menunjukkan bahwa otonomi seni tidak sinonim dengan sikap apolitis. Justru ia sangat bisa dimaksudkan untuk menjadi politis. Premis yang melatari kekaryaan Brouwer dan otonomi seni yang dibela Adorno adalah salah duanya. Contoh lain: pasca Perang Dunia Kedua, para pelukis abstrak yang bermunculan di Amerika mengklaim diri bebas nilai dan apolitis. Belakangan hal itu terbukti keliru. Fakta bahwa gerakan seni rupa abstrak (juga bidang seni lainnya yang mengaku mengemban nilai-nilai humanisme universal) ditukangi CIA selama masa Perang Dingin dapat membikin kita terjungkal (Saunders, 2000; Herlambang, 2011). Apa yang kita kira apolitis, justru terang-benderang politis: seni rupa abstrak adalah rayuan neoliberalisme Barat tentang kebebasan murni.
Mendeklarasikan Kebenaran
Sebagai metode, estetika Marxis juga terbuka dan aplikatif terhadap perkembangan sejarah yang dialektis. Ini juga dasar mengapa doktrin Marxisme di wilayah seni selalu dinamis, alih-alih dogmatis dan propagandis. Dalam perjalanannya, seperti yang sudah kita lihat, para Marxis seperti Trotsky, Bloch, Brecht, dan Adorno, punya formulanya sendiri dalam memandang seni. Meski berbeda satu sama lain, mereka memiliki satu benang merah serupa: menghalalkan eksplorasi dan kebaruan bentuk.
Karena itu, sebuah karya selalu dapat ditinjau sebagai suatu hubungan sosial yang menyejarah sekaligus sebagai suatu perjalanan sejarah seni. Maka, karya seni bukanlah hasil pemikiran individu seniman yang terisolasi dari sejarah, melainkan selalu terkondisikan oleh sejarah. Seorang seniman dapat dibedakan dengan seniman lainnya persis karena mereka memiliki kondisi material yang berbeda dan karena mereka mengidentifikasi dirinya dari satu perjalanan sejarah. Sehingga, dengan kesadaran tertentu, seorang seniman rupa tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan oleh Picasso atau Affandi, misalnya, secara artistik. Dengan demikian, kenyataan material (ekonomi-politik) harus selalu dijangkarkan di dalam sebuah karya seni sekaligus menjawab pertanyaan: apakah karya tersebut menawarkan kebaruan bentuk dan artistik dalam usahanya menjawab sebuah perjalanan sejarah seni?
Dalam penciptaan seni, kenyataan material bukanlah semata kenyataan yang universal, melainkan kenyataan material yang diresapi secara personal. Material personal yang ditanam di dalam karya inilah yang kemudian mengemuka sebagai kekhasan seorang seniman sebagai subjek yang berpikir dan merasa. “Ada beberapa elemen yang begitu kuat yang melatari saya. Terutama musik ritual masyarakat Afrika-Kuba, yang didedikasikan untuk para dewa. Ini sesuatu yang mengesankan saya sejak saya berumur sembilan tahun,” begitu kata Brouwer. Dan material personal itulah yang membedakannya dengan Schoenberg, kendati keduanya sama-sama berusaha membongkar dominasi yang sama.
Pasca-Revolusi Kuba, Brouwer dipercaya menduduki beberapa posisi strategis di birokrasi. Sejak tahun 1964 hingga akhir dekade 1990-an, misalnya, ia mengepalai divisi musik di Lembaga Film Kuba (ICAIC), anggota kehormatan Dewan Musik Internasional UNESCO sekaligus representatif untuk negaranya, dan menjadi penasihat musik untuk Menteri Kebudayaan Kuba. Ini juga menjadi bukti bahwa panorama kebudayaan Marxisme tak sekering yang dibayangkan orang. Bahwa apa yang terjadi di Soviet bukanlah fakta tunggal kegagalan Marxisme, apalagi kegagalan dalam mengimajinasikan kesenian yang merepresi kebebasan artistik individu.
Sebaliknya, karya seni justru kian seragam di hadapan pasar. Di sini, alih-alih membebaskan individu seniman, kapitalisme secara tidak sadar justru membelenggu individu. Istilah “sesuai selera pasar” kemudian menjadi suatu doktrin otoriter yang memenjarakan kreativitas. Seni kehilangan daya kritisnya, bahkan terhadap dirinya sendiri, yang pada gilirannya malah menciptakan krisis kebudayaan. Film waralaba berjilid-jilid adalah salah satu contohnya.
Penting bagi kita untuk menengok kembali estetika Marxis sebagai metode dalam meninjau peristiwa kesenian hari-hari ini. Saya kira ini dapat menjadi satu alternatif sekaligus kritik terhadap pemikiran postmodern yang melingkupi berbagai kajian dan penciptaan seni di Indonesia. Kita, misalnya, lebih sering terjebak dalam perayaan terhadap keberagaman tanpa punya sikap kritis untuk menjangkarkan berbagai peristiwa artistik itu ke kenyataan ekonomi-politik dan kesadaran kelas.
Estetika Marxis, dengan begitu, dapat menjadi jawaban dari absennya kebenaran di dalam sebuah aktivitas membaca dan mencipta karya. Bahwa seni mengandung kebenaran, dan tidak mengandung nilai-nilai relatif yang hanya membuat kita meratapi keadaan, penting untuk dideklarasikan kembali. Dan kebenaran bagi Marxisme, penulis kira, selalu dapat diamini sebagai hipotesis tentang kesetaraan.
Daftar Pustaka
Adorno, Theodor. Philosophy of New Music. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
Arvon, Henri. Marxist Esthetics. Ithaca and London: Cornell University Press, 1973.
Bloch, Ernst. The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays. Studies in contemporary German social thought. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.
Brecht, Bertolt. Aesthetics and Politics. London: Verso, 1980.
Herlambang, Wijaya. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Jakarta: Marjin Kiri, 2011.
Lifshitz, Mikhail. The Philosophy of Art of Karl Marx. London: Pluto Press, 1973.
Saunders, Frances Stonor. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press, 2000.
Suryajaya, Martin. Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer. Jakarta: Gang Kabel, 2016.

Almer Sidqi
Alumnus musikologi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Meminati kajian seni, filsafat, dan politik. Saat ini bekerja sebagai jurnalis.

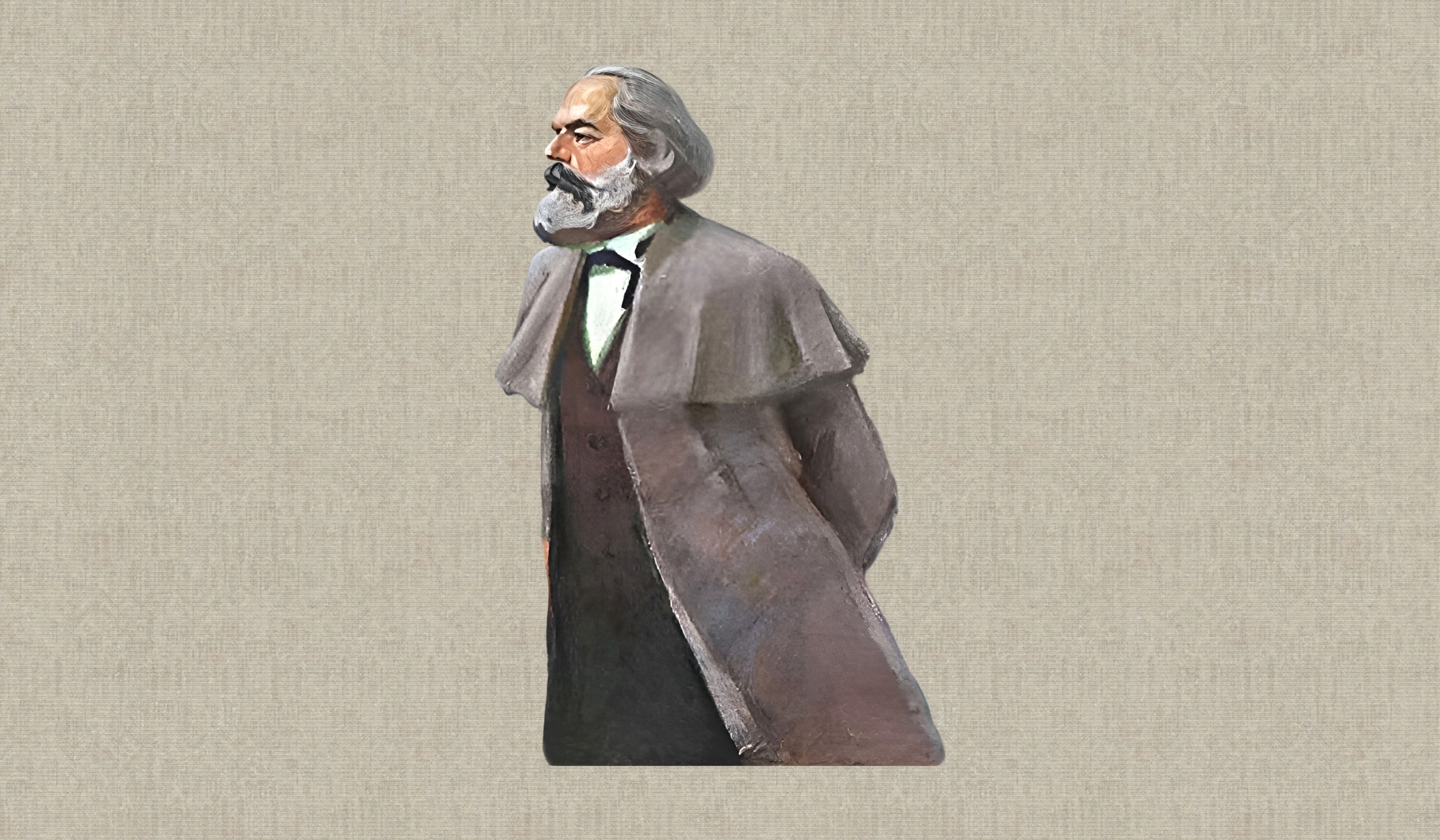






Berikan komentar