Selama ini kita dicekoki logika Aristoteles (logika klasik) yang hanya memberikan dua kemungkinan proposisi: proposisi tersebut benar atau salah. Hukum bivalensi ini kemudian menghasilkan tiga aksioma logika klasik: prinsip identitas A = A, prinsip non-kontradiksi ¬(A Ʌ¬A), dan prinsip ketiadaan jalan tengah A v ¬A. Dalam matematika, logika klasik digambarkan secara simbolik dalam hukum Aljabar Boolean dengan dua nilai konstanta 1 atau 0. Maka seluruh operasi aritmetika hanya memiliki dua kemungkinan kesimpulan: 1 (benar) atau 0 (salah).
Model kebenaran hitam-putih ini membuat pikiran kita sulit menerima apa yang selama ini tak diizinkan hadir dalam operasi logika klasik: kontradiksi A Ʌ¬A. Di samping dianggap tidak bermakna, kontradiksi bagi logika klasik hanya akan menghasilkan kondisi ex contradictione quodlibet atau ledakan: dari kontradiksi kita bisa membuat segalanya menjadi benar. Contoh kontradiksi bisa ditemukan pada argumen “paradoks pembohong”. Misalnya, pernyataan “kalimat ini salah”. Jika pernyataan ini salah, maka benar. Tapi jika pernyataan ini benar, berarti salah karena isinya menyatakan demikian. Hasilnya kontradiksi. Karena pernyataan tersebut bisa benar sekaligus salah.
Kasus tersebut juga marak ditemukan dalam matematika. Kita tahu bahwa dalam tubuh matematika juga tertancap kuat pandangan absolutisme yang memandang matematika dapat mencapai kebenaran mutlak melalui operasi logika. Paul Ernest mengatakan, pandangan absolutis tentang pengetahuan matematika didasarkan pada dua jenis. Yakni asumsi matematika, tentang asumsi aksioma dan definisi, dan logika tentang asumsi aksioma, aturan inferensi dan bahasa formal dan sintaksisnya.1
Namun, ternyata pandangan absolutis menghadapi masalah di awal abad kedua puluh ketika sejumlah antinomi dan kontradiksi diturunkan dalam matematika. Misalnya teori Basic Law V Gottlob Frege, formulasi paling ketat dari logika matematika yang dikenal di masanya, menunjukkan suatu kontradiksi yang dibuktikan oleh Russell pada 1902. Dalam Basic Law V, suatu himpunan dapat dibuat agar suatu properti dapat diterapkan pada himpunan tersebut. Tapi Russell menunjukkan paradoks dari teori tersebut dengan cara mendefinisikan properti “tidak menjadi elemen dari dirinya sendiri”.2
Untuk memperjelas “paradoks Russell” ini, anggaplah R adalah himpunan yang berisi objek yang tidak menjadi elemen dari dirinya sendiri. Jika digambarkan dalam teori himpunan, notasinya seperti ini: R = {x ∣ x ∉ x}. Notasi tersebut artinya, x adalah R jika dan hanya jika x bukan elemen dari x. Sekarang mari membuat pilihan, apakah R ∊ R atau R ∉ R. Himpunan tersebut akan menghasilkan kontradiksi jika R hendak dimasukkan sebagai anggota dalam himpunan R. Karena jika R ∊ R, maka R ∉ R. Tapi jika R ∉ R, maka R ∊ R.
Krisis matematika tersebut membuat Ernest memunculkan pertanyaan yang patut direnungkan: “Temuan semacam itu, tentu saja, memiliki implikasi serius bagi pandangan absolutis tentang pengetahuan matematika. Karena jika matematika itu pasti, bagaimana dengan kontradiksi di antara teorema-teoremanya?”3 Pertanyaan tersebut akhirnya memunculkan keraguan jika logika klasik tak selamanya bisa berlaku dalam semesta matematika yang pada dirinya bisa menghasilkan kontradiksi.
Paraconsistent logic atau sering pula disebut logika paradoks hadir menjawab kebuntuan tersebut, dengan menerima kontradiksi sebagai sesuatu yang valid dalam logika. Pesohor paraconsistent logic Graham Priest dalam artikelnya berjudul What is so Bad about Contradictions? (1998) percaya jika beberapa dari kontradiksi adalah benar. Kata “beberapa” demikian kata Priest, tentu berbeda dengan kata “semua”. Membenarkan beberapa kontradiksi akan berbeda penekanannya dengan mengatakan semua kontradiksi adalah benar. “Tentu tidak rasional untuk percaya bahwa saya adalah telur goreng,” kata Priest. Sehingga tak rasional untuk percaya bahwa “saya adalah telur goreng dan bukan telur goreng”.4
Namun bagaimana pun, kontradiksi bisa diterima jika argumennya masuk akal dan tidak meledak atau absurd. Untuk kasus kontradiksi dari “paradoks pembohong” dan “paradoks Russell”, penganut paraconsistent logic seperti Priest menerimanya dengan membuat satu model kebenaran yang baru: benar sekaligus salah. Karena seperti itulah konsekuensi logisnya. Sikap cair logika paradoks terhadap kontradiksi membuat model penalaran tersebut tak melulu memandang interpretasi hanya menghasilkan benar atau salah. Logika paradoks memandang fakultas logika memiliki ruang yang lebih beragam yang bisa dilihat pada himpunan rumus berikut:
| Tidak benar dan tidak salah | Salah |
| Benar | Benar sekaligus salah |
Bagi Priest, kalimat “di luar sekaligus di dalam ruangan” benar dan logis jika kita berada di ambang pintu dan secara simetris satu kaki berada di luar dan kaki lainnya berada di dalam ruangan. Saat berada di posisi itu, kita tidak di dalam dan tidak di luar, atau di dalam dan tidak di dalam ruangan. Artinya pernyataan tersebut bisa dimasukkan dalam kotak kanan bawah.5 Sama halnya pernyataan, “Besok akan ada pertempuran laut”. Kalimat kontingen masa depan seperti itu tak bisa dinilai benar atau salah. Sehingga kita bisa memberi kesimpulan kalimat tersebut tidak benar dan tidak salah. Olehnya itu, ia bisa dimasukkan dalam kotak kiri atas.6
Terlepas dari banyaknya upaya untuk membantah model paraconsistent logic, namun setidaknya, logika tersebut pelan demi pelan membuka cakrawala berpikir kita: dunia ini tak sesempit oposisi biner Aristotelian yang statis dan kaku. Masalah dari paraconsistent logic adalah jenis logika ini lebih condong mengurai masalah paradoks semantik dan tidak bekerja keras untuk membela kontradiksi dalam realitas. Namun paraconsistent logic telah memberi insight pada kita, bahwa ada kalanya kita membutuhkan logika yang berbeda pada domain yang berbeda. Untuk menelusuri kemungkinan kontradiksi dalam realitas, kita membutuhkan logika dialektis (dialektika), metode berpikir yang bisa ditelusuri dalam sistem filsafat Hegel dan Marxisme.
***
Jauh sebelumnya G.W.F Hegel sudah dengan tegas menyatakan jika segala realitas mengandung negasinya sendiri—artinya mengandung kontradiksi. Sebagaimana yang diungkapkan Hegel dalam Science of Logic, “Tidak ada sesuatu pun di langit atau di alam atau roh yang tidak mengandung ada dan ketiadaan.”7 Jika hendak ditafsirkan, Hegel hendak mengatakan jika setiap entitas mengandung ada dan ketiadaan, positif dan negatif, identitas dan non-identitas secara bersamaan. Melalui kontradiksi ini setiap entitas melakukan proses dialektis dengan negasinya sendiri dan membentuk sejarah panjang alam semesta.
Hegel dalam Phenomenology of Spirit menggambarkan gerak alam yang dialektis tersebut melalui proses manifestasi diri Roh. Bermula dari Roh sebagai kesadaran diri dan substansi abstrak yang mengeksternalisasi atau merealisasikan dirinya menjadi alam semesta dan segala isinya. Roh akhirnya menyadari telah mengasingkan dirinya dan sekaligus menyadari alam semesta adalah dirinya sendiri. Hingga Roh mencapai pengetahuan tentang dirinya sendiri dan memproklamasikan dirinya sebagai Roh Absolut. Hegel kemudian membagi realisasi diri Roh tersebut dalam tiga momen perkembangan Roh:
- Dalam bentuk hubungan diri: Di dalamnya memiliki cita-cita totalitas Ide, keberadaannya mandiri dan bebas. Perkembangan pertama ini disebut Roh Subjektif.
- Dalam bentuk kenyataan: Terwujud di dalam dunia yang diproduksi oleh Roh. Perkembangan kedua ini disebut Roh Objektif.
- Kesatuan Roh Objektif dan Roh sebagai idealitas dan konsep (Roh Subjektif) menghasilkan dirinya sendiri, Roh sebagai kebenaran mutlak. Perkembangan ketiga ini disebut Roh Absolut. 8
Tiga momen perkembangan Roh telah menunjukkan secara eksplisit cara kerja dialektika melalui hubungan kontradiktif antara Roh dan alam semesta. Roh Subjektif (tesis) merealisasikan dirinya sendiri dalam bentuk alam semesta atau Roh Objektif (antitesis). Hubungan timbal balik dan penyatuan antara keduanya menciptakan suatu pengetahuan baru tentang Roh. Roh Subjektif menyadari jika alam semesta adalah dirinya sendiri tapi dalam bentuk yang lain. Kesadaran ini membuat Roh mengetahui dirinya sebagai Roh Absolut karena adanya alam semesta sebagai realisasi dirinya (sintesis).
Fenomenologi Roh dari Hegel perlu dipaparkan di sini guna memperjelas maksud Hegel mengenai realitas mengandung negasinya sendiri. Jika dicermati dengan baik, alam semesta dan segala isinya identik sekaligus berbeda dengan Roh. Artinya, alam adalah Roh sekaligus bukan Roh: alam semesta mengandung negasinya sendiri. Untuk memperjelas pernyataan membingungkan ini, saya akan meminjam argumen dari pakar Hegel Indonesia, Fitzerald:
“Seluruh kenyataan ini identik dengan Roh karena kenyataan ini tidak lain dari hasil manifestasi-diri Roh; kenyataan ini pada hakikatnya adalah Roh itu sendiri, namun dalam bentuk yang lain, yakni dalam bentuk yang material atau terbatas. Roh itu sendiri immaterial dan tidak terbatas, namun ia membuat diri-Nya menjadi material dan terbatas. Itulah alam semesta dan segala isinya. Itu berarti, Roh terdapat juga dalam kenyataan ini justru karena kenyataan ini adalah hasil realisasi dirinya, seluruh kenyataan ini adalah Roh dalam bentuk yang-lain; karena itu, esensi kenyataan ini justru adalah Roh itu sendiri.”9
Pernyataan di atas tentu sangat sulit dipahami jika menggunakan operasi logika klasik. Tapi dengan menggunakan pendekatan dialektika, kita bisa menyimpulkan jika alam semesta adalah identik sekaligus berbeda dari Roh. Menariknya juga, berdasarkan pada momen perkembangan diri Roh, ternyata Roh dapat mengidentifikasi dirinya sebagai Roh jika berelasi dengan alam semesta sebagai negasinya. Hegel sendiri pernah mengatakan dalam Phenomenology of Spirit jika, “sesuatu adalah satu karena dipertentangkan dengan yang lain. Tapi sesuatu itu bukan satu ketika yang lain dikecualikan dari dirinya. Karena menjadi satu adalah hubungan universal antara diri dengan dirinya sendiri, dan fakta bahwa dia adalah satu yang membuatnya seperti yang lain, dan melalui tekadnya dia juga tidak termasuk yang lain.”10
Pernyataan Hegel tersebut tak hanya menyiratkan kontradiksi pada suatu entitas: prinsip non-kontradiksi logika klasik tak berlaku. Namun keberadaan dan identitas suatu entitas selalu mengandaikan keberadaan lain yang bukan dirinya. Sebagaimana Roh mengidentifikasi dirinya sebagai Roh Absolut karena bergantung secara konstitutif terhadap keberadaan negasinya, yakni alam semesta. Hal tersebut juga berlaku pada entitas lainnya. Misalnya gelas bisa didefinisikan sebagai gelas jika semua non-gelas terdapat pada gelas dalam bentuk negatif. Kebergantungan gelas pada non-gelas membuat gelas tak selalu sama dengan dirinya sendiri. Karena ketika non-gelas tidak mendeterminasi gelas, maka gelas tak bisa disebut sebagai gelas. Sebagaimana kata Hegel, “sesuatu itu bukan satu ketika yang lain dikecualikan dari dirinya.”. Artinya prinsip identitas logika klasik yang memandang sesuatu identik dengan dirinya sendiri tak berlaku pada realitas yang kontradiktif.
Inilah yang sering dibilangkan sebagai dialektika. Yakni, cara berpikir yang melihat segala sesuatu bersifat kontradiktif.11 Ketika logika klasik Aristotelian tidak mengizinkan kontradiksi, dialektika justru menerimanya. Sifat kontradiktif ini juga yang membuat realitas selalu berubah. Sebagaimana yang diungkapkan Martin Suryajaya: “Berdasarkan konsepsi dialektika sebagai negasi internal inilah Hegel dapat menteorikan ontologi yang memberikan peran utama pada gerak dan perubahan: oleh karena semua entitas telah mengandung negasinya sendiri maka tak ada entitas yang sepenuhnya tetap, semuanya dapat berubah begitu negasi internal tadi dieksplisitkan.”12
Hanya saja dialektika Hegel dalam sejarahnya, mendapatkan kritikan yang keras terhadap Karl Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Karena gagasan tentang Roh itu, Hegel dianggap masih dibayang-bayangi oleh argumentasi kaum mistis dan dituduh sebagai seorang idealis. Karena hanya memosisikan realitas objektif sebagai penyebaran diri dari Roh. Lagi pula, dialektika Hegel tak tegas memilah-milah mana ranah epistemologi dan mana ranah ontologi. Seolah-olah makna, hakikat, dan identitas sesuatu yang dikonseptualisasikan juga berlaku pada realitas objektif . Sehingga ada kesan realitas objektif bisa diandaikan ada setelah dipikirkan oleh manusia.
Engels dalam Kata Pengantar Lama Pada Anti-Duhring (1878) mengatakan, dialektika Hegel berangkat dari pemahaman bahwa jiwa, pikiran, ide, adalah primer dan bahwa dunia real hanyalah sebuah salinan dari ide. Oleh karena itulah Engels dengan keras mengkritik dialektika Hegel dengan menyebut “konstruksi (rancang-bangun) sistem dialektika Hegel terlalu sewenang-wenang dan mengingkari fakta.”
Selain itu, dialektika Hegel dikritik dalam hal konstruksi subjeknya. Marx, sebagaimana yang diungkapkan Balibar, berpandangan bahwa “aktivitas subjektif yang dibicarakan oleh idealisme, pada dasarnya, merupakan jejak atau denegasi (pengakuan sekaligus pengabaian) dari sebuah aktivitas yang lebih kongkret, sebuah aktivitas yang lebih ‘memiliki efek’….. yang pada suatu saat dan pada saat yang sama membentuk dunia eksternal dan sekaligus membentuk (building) atau mentransformasi diri.”13
Karl Marx yang kelak disempurnakan oleh Engels akhirnya merumuskan suatu model dialektika yang lebih organik dan realis: dialektika materialis. Sistem filsafat Marxisme ini membawa dialektika dari Roh dan ditempatkan di dunia objektif yang empiris. Hukum-hukum dialektika yang semula abstrak dan diposisikan sebagai hukum-hukum pikiran, “di-bumi-kan” menjadi hukum-hukum alam. Justru hukum-hukum dialektika alam yang menentukan hukum-hukum dialektika dalam pikiran.
Meski dialektika diformat dalam sistem materialisme, namun dialektika materialis tetap mengakui kontradiksi sebagai sesuatu yang nyata dalam realitas objektif. Justru melalui kontradiksi, realitas objektif jadi lebih hidup dan dinamis dalam gerak dan perubahan. Di sisi lain, perubahan akibat dialektika alam membuat realitas tak selalu hadir pada dirinya sendiri. Olehnya itu, hukum identitas logika klasik tetap tak berlaku jika dihadapkan pada hukum-hukum objektif dialektika alam.
Melalui hukum dialektika itulah alam berkembang melalui relasi saling memengaruhi antar entitas. Engels menyebut alam semesta sebagai suatu sistem di mana benda-benda mulai dari bintang-bintang, atom-atom, hingga partikel-partikel saling terkait. Hubungan relasional tersebut membuat benda-benda bereaksi satu sama lain melalui daya tarik dan daya tolak. Aksi timbal balik yang saling menarik dan berlawanan ini kemudian menghasilkan gerak. Singkatnya, gerak pada realitas objektif disebabkan oleh kontradiksi antar benda.
Pun, sebagaimana yang ditekankan Engels, dialektika antar benda membuat suatu benda dapat berubah kualitas akibat penambahan dan pengurangan kuantitas. Seperti cairan mempunyai titik beku dan titik didih jika suatu instrumen memungkinkan untuk memproduksi suhu yang diperlukan. Penjelasan ini tak hanya menunjukkan sifat kontradiktif dari realitas objektif, namun juga akibat gerak dan perubahan, setiap entitas tak pernah dalam keadaan tetap.
Itu artinya, dalam alam semesta, tak ada objek yang tetap pada dirinya sendiri. Atau prinsip identitas dalam logika klasik tak berlaku dalam realitas objektif. Sungai akan kehilangan identitas jika bertemu laut dan berubah menjadi muara. Begitu pun kertas tak bisa tetap menjadi kertas jika dilahap api. Karena kertas akan menjadi abu. Dialektika alam objektif ini dalam perspektif dialektika materialis, akhirnya membentuk struktur pikiran manusia tapi tidak secara determinan mutlak. Karena manusia juga memiliki kebebasan untuk memengaruhi perubahan realitas melalui praxis.

Muhajir MA
Muhajir MA adalah seorang jurnalis dan peminat kajian filsafat dan ilmu sosial. Sekarang tinggal di Makassar.
Catatan
- Paul Ernest, The Philosophy of Mathematics Education: Studies in Mathematics Education, (London: Routledge), 1991, hlm 8.
- Ibid.
- Ibid.
- Graham Priest, What is so Bad about Contradictions? The Journal of Philosophy, Vol. 95, No. 8 (1998), hlm 410.
- Ibid, hlm 415.
- Ibid, hlm 414.
- G.W.F Hegel, Science of Logic, Diterjemahkan oleh George Di Giovanni (Cambridge University Press), 2010, hlm 45
- G.W.F Hegel, Hegel’s Philosophy of Mind: Translated From The Encyclopaedia of The Philosophical Sciences, diterjemahkan oleh William Wallace, M.A, LL.D (Oxford: At The Clarendon Press, 1894), hlm 8
- Fitzerald Kennedy Sitorus, Allah dan Trinitas: Sebuah Pendasaran Dialektis-Filosofis Hegelian, Jurnal STFT Vol VII, No 1, 2019, hlm 9
- G.W.F Hegel, Phenomenology of Spirit, diterjemahkan oleh A. V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), hlm 72-73
- Fitzerald Kennedy Sitorus, op.cit, hlm 10
- Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis: Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer (Yogyajarta: Resist Book), 2012, hlm 61
- Etienne Balibar, Anti Filsafat: Metode Pemikiran Marx, diterjemahkan oleh Eko P. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2013) hlm 46

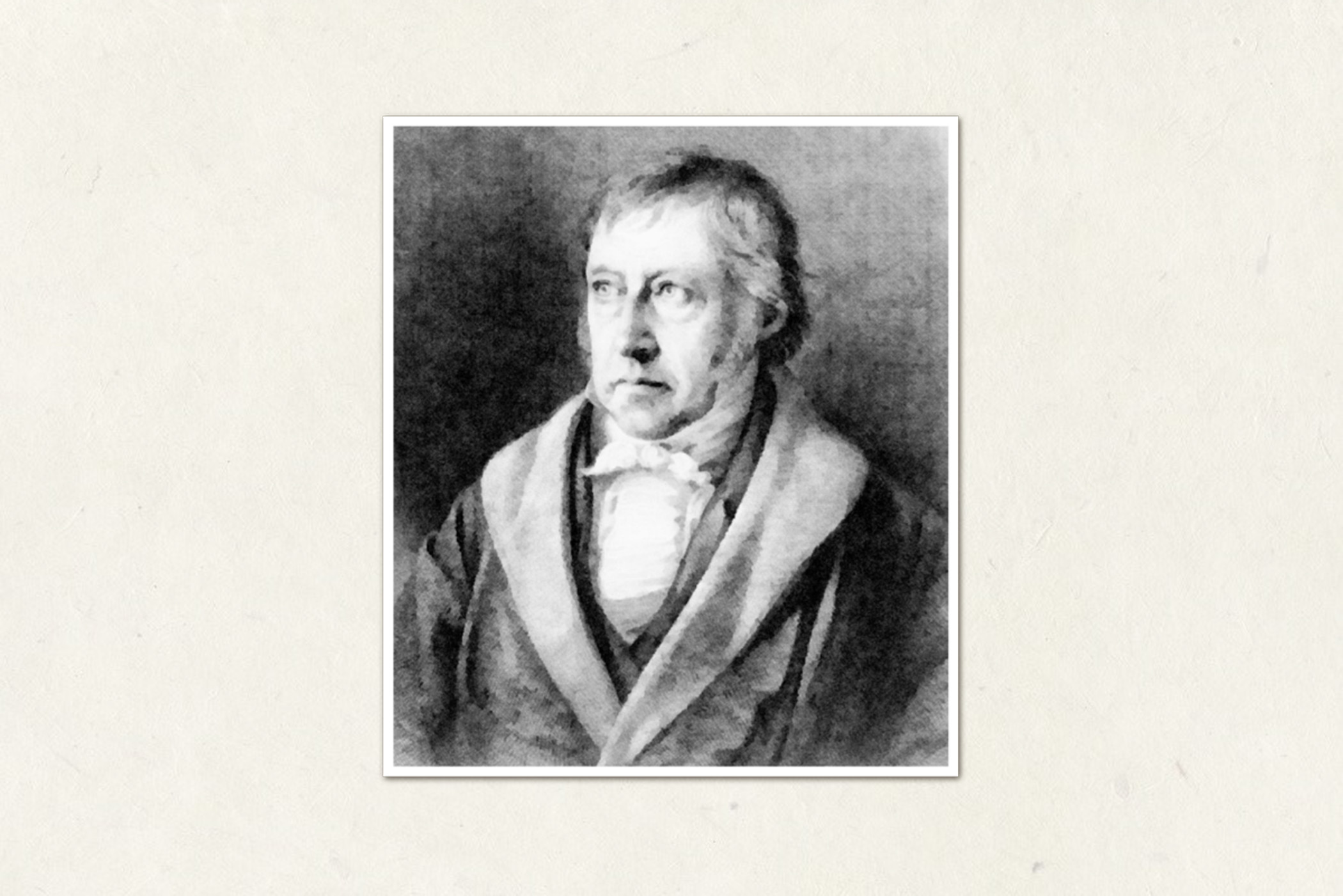







Berikan komentar