Bagaimanakah nalar yang jernih seharusnya diuji? Bagaimanakah akal sehat bisa mengalami benturan politis? Benarkah telah terjadi semacam intellectual culdesac di kalangan akademisi dan ilmuwan sampai-sampai ujaran dan pikiran sampah seorang Rocky Gerung diberi panggung oleh media nasional layaknya kaum Sofis? Benarkah telah terjadi politisasi akal sehat demi politik elektoral menjelang Pilpres? Apakah acara ILC bisa dikategorikan sebagai ruang publik? Yang tak kalah penting, apakah filsafat juga akan mengalami pembusukan? Tulisan singkat ini adalah usaha kecil untuk (tidak) menjawab dan membincang kecamuk tanya di atas. Baik, siapkan kopi dan akal sehat Anda!
Di Eropa abad pertengahan—yang lazim disebut dark age (zaman kegelapan)—teologi selalu tampil sebagai “sang domina”, pengangkang filsafat sekaligus pendera sains. Praktis, para filsuf dianggap anti agama, anti doa, musuh agama dan memang filsafat itu bukan mantra sekaligus doa. Inilah ujian penting akal sehat secara sistematis-struktural.
Sebagaimana tidak semua orang butuh filsafat, tidak setiap orang pula butuh agama. Mengapa? Hidup tak selalu berkorelasi dengan keduanya. Apa sebab? Tiap manusia tidak sama, tiap tempurung pasti berbeda. Sains tidak butuh agama, dan agama tidak memerlukan sains untuk diimani serta dijalani pemeluknya, meskipun faktanya kaum bumi datar sangat gandrung dengan cocokologi agama. Namun demikian, manusia membutuhkan sains dan agama. Fritjof Capra menambahkan dalam magnum opusnya The Tao of Physic, bahkan manusia membutuhkan mistik untuk menjalani hidupnya.
Meski tak semua butuh agama, agama tak pernah mati. Memang, modernisasi membonceng sekularisasi, tapi sekularisme—setelah pada dekade 70-80an merajalela—menjadi dagangan basi: nasi sudah menjadi bubur dan bubur telah basi. Itu artinya sekularisasi dalam sains dan dunia politik, tidak otomatis berimbas pada agama dan penyangga-penyangganya berupa kebudayaan, tradisi, kearifan lokal dan suprastruktur lainnya.
Alih-alih mengalami kematian, agama justru kian banyak diminati. Kini, tak hanya orang modern terpelajar, bahkan kaum cuti nalar dan mabuk agama sekalipun merasa perlu “kembali” ke agama, kembali ke Qur’an-Hadits, tentu saja karena mereka merasa telah meninggalkan agama.
Kita tahu bahwa revolusi Eropa tak hanya merobohkan tembok Berlin, tapi juga sistem komunis Soviet. Persis, telah terjadi Balkanisasi, yakni bangkitnya sentimen-sentimen suku dan agama bersamaan dengan runtuhnya gigantisme Uni Soviet. Lagi-lagi, akal sehat dan nalar kritis harus terperangkap oleh dogma untuk kedua kalinya.
Sentimen kesukuan yang sebelumnya ditindas melahirkan gerakan etnosentrisme, sementara keagamaan yang sekian lama dikekang melahirkan fundamentalisme. Keduanya praktis menjadikan “hantu” baru pasca komunisme. Tapi anehnya, isu komunisme masih laku dijual di kalangan kaum defisit otak.
Nah, tumbangnya Orde Baru di Indonesia lebih-kurang membawa konsekuensi logis seperti yang terjadi di Eropa. Maka, menjamur ormas-ormas yang kalau tidak etnosentris ya fundamentalis setelah bergulir reformasi. Cepat dan pasti, menyeruak teror-teror yang menganggap—dengan meminjam istilah Wolfgang Huber—”kekerasan sebagai ibadah” (gewalt als gottesdienst).
Kekerasan atas nama agama merentang sejak 9/11, rangkaian bom Bali, Jakarta, Solo, Surabaya, Ambon, teror ISIS di berbagai kota dan negara, hingga pembakaran gereja dan persekusi terhadap non-muslim. Kekerasan jenis ini jelas-jelas mencoreng-moreng agama hingga koyak-moyak dan boyak. Memang, kekuasaan (power), kekuatan (force), dan wewenang (authority) bagi terjadinya kekerasan ini sangat berjalin-jemalin dengan politik global, akan tetapi (pseudo) “kebangkitan” agama pasca Balkan dan Orde Baru sangat menghambat proses penyembuhan luka selama 32 tahun. Apa sebab? Kebangkitan agama bukan kebangkitan sebagaimana ia diwahyukan pertama kali dan diajarkan para Nabi. Inilah ujian berikutnya bagi akal sehat dan pada saat yang sama merebak pembusukan nalar di ruang publik.
Memang, nilai-nilai sekular khas Eropa, seperti HAM, ideologi pasar alias kapitalisme, ideologi sains alias naturalisme, ideolog politik alias liberalisme, dan yang tak kalah penting ideologi kelamin, yakni LGBTIQ kian populer di Indonesia dewasa ini. Anda juga sudah tahu siapa yang membiayai itu semua!
Sementara itu, media sosial tak ubahnya ladang subur bagi para pembenci, pencaci, mencemooh, pencemar, penggunting dalam lipatan, pembegal, pemancing, tengkulak keributan, pengembang provokasi, makelar propaganda dan peselancar negatif demi kepentingan gerombolan serigala berbulu ormas dan para pemangsa sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ideologi (Pancasila). Sungguh-sungguh nyata bahwa ketiga sumber daya tersebut, khususnya sumber daya alam adalah sasaran empuk para pemangsa yang kerap kali luput dari akal sehat dan sikap kritis kita, juga para warganet.
Digoreng dengan bumbu-bumbu politik, ditumis dengan aroma dan saus agama yang penuh intrik, direbus bersama kaldu sentimen etnik, dipanggang dengan bara isu komunis dan lantas disajikan di mulut-mulut mayoritas awam sebagai menu sehari-hari, tengik tapi nampak asyik, bikin ketagihan meski menyesatkan. Satu berita diviralkan dan oleh buzzer-buzzer bayaran lalu diproyeksikan—misalnya—untuk mendiskreditkan golongan tertentu, menghujat yang berbeda agama dan paham, menjatuhkan lawan politik, menjegal kompetitor bisnis, menggulingkan penguasa, dan bahkan hendak mengganti ideologi Negara dengan dalih memperjuangkan “akal sehat”. Satu istilah yang belakangan ini dikaburkan oleh para tengkulak. Inilah ujian berikutnya bagi filsafat, yakni politisasi dan pembusukan filsafat secara sistematis di ruang publik.
Kepentingan para predator bisnis, para oligark politik, para begundal demokrasi, para bromocorah penjual hukum, para tengkulak isu SARA, para cecunguk pengasong khilafah yang dibungkus rapi dengan muslihat “bela agama” melalui gerakan masif populisme Kanan sungguh telah menghina akal sehat bangsa Indonesia.
Artinya, gerakan ini bukan inisiatif rakyat, bukan pula berangkat dari kesadaran umat, kerana para predator itu jelas-jelas “menyerang” ego, bukan rasio! Dengan kata lain, kemarahan publik berangkat dari “kesadaran palsu” yang dibentuk para tengkulak oligarki melalui media (sosial) secara masif dan terencana. Sudah tahu bukan tukang goreng, tukang kipas, dan tukang sabunnya, juga para bandar yang membiayai mereka?
Berbeda dengan populisme Kiri yang progresif-demokratis, populisme Kanan malah anti-demokrasi, ultra-konservatif plus kolot 14 turunan. Populisme Kanan adalah gerakan menggiring kemarahan rakyat/umat (populus) kepada pemerintah dan rezim. Emosionalisasi politik SARA dengan provokasi dan demagogi yang keji serta ujaran kebencian ultra-jahiliyah sebenarnya bukan hal baru, ia sudah sangat kuno tapi lumayan mujarab bagi masyarakat tuna pustaka dan generasi milenial alergi baca, bahkan sangat ampuh bagi kaum otak cingkrang, bani cuti nalar permanen, kaum pentol korek-sumbu pendek, dan panasbung (pasukan nasi bungkus) pengasong simbol agama dan pemburu bulu ketiak bidadari.
Penguasaan basis-basis kognitif oleh media, konsensus penggiringan opini, penyebaran opium-opium faktual dan krusial agar masyarakat mabuk agama, puber simbol-simbol keagamaan dan kehilangan sikap kritis, bahkan konstelasi budaya dan kesenian dicemari sedemikian gila oleh pandangan-pandangan represif dan destruktif berbasis agama. Yang menggerakkan media, yang membiayai para pemodal dan proksi-proksi penguasa, yang diserang ego kaum otak cingkrang, pirantinya teknologi informasi, pemanisnya ayat-ayat suci. Kalau kita menolak mereka, segara kita dituduh anti agama!
Pertanyaan lugu yang bisa kita sodorkan adalah: setelah agama manjadi pendera yang menghapus kesenian dan kebudayaan, setelah agama mencambuk sains dan teknologi dan memaksa keduanya menjadi budak agama, bahkan setelah (ideologi dan sistem) negara dicabik-cabik oleh agama, setelah tak ada yang tersisa selain agama, masih adakah akal sehat? Kini, agama berhadap-hadapan dengan ego yang tadinya mengendalikan agama demi kepuasan tak berujung, syahwat berkuasa semata-mata. Setelah tak ada lagi pintu-pintu konspirasi, bersiap-siaplah agama untuk meledakkan dirinya sendiri di dalam ego: kalah jadi abu, menang jadi arang, ditelan menjadi racun, dimuntahkan menjadi api!
Belakangan, Carl Schmitt, dalam Politische Theologie menyatakan bahwa semua konsep padat dalam teori negara modern adalah konsep-konsep teologis yang dusekularkan. Mengapa?
Mari kita ingat kembali teori negara-negara modern, misalnya teori kontrak dari Thomas Hobbes, John Locke dan J. J. Rousseau, juga konsep-konsep politik modern yang tumbuh dalam filsafat Jerman, bahkan konsep negara hukum (rechtsstaat) Belanda, serta trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) ala de Montesquieu, semua pandangan itu terasa betul masih mengandung asumsi-asumsi teologis dan memang berhamburan ayat dan hadits yang melegitimasi itu semua. Ini membuktikan bahwa filsafat Barat yang sekular sekalipun tidak pernah menggeliat di ruang hampa, bernalar di atas altarnya sendiri, ia tetap (sebagiannya) merupakan warisan tradisi iman tertentu.
Kerumunan yang murka melalui aksi demo berjilid-jilid dan bersilit-silit, politisasi agama dan agamaisasi politik, sentimentalisasi politik dan politik sentimen mengarah rasis adalah ciri utama yang paling mencolok dari gerakan populisme Kanan. Hasilnya apa? Jutaan kaum monaslimin-monaslimat alumni gerakan populisme Kanan itu yang mereka tidak tahu-sadari kecuali sebagai bela agama, titik! Para tengkulak untung, para predator senang, toleransi buntung, kebinekaan mengalami turbulensi, lalu terjun bebas bersama akal sehat.
Gembong-gembong populisme, misalnya Trump di Amerika Serikat, Greet Wilders di Belanda, Le Pen di Prancis, Jair Bolsonaro di Brazil, Lutzbachman di Jerman dan beberapa nama di Indonesia sangat efektif membangun citra seperti “obat kuat” bagi para pengikutnya serta manjadi “ego-ideal” bagi para pemujanya. “Kuat” terhadap apa? Kuat untuk cuti nalar dan tidak kritis sampai-sampai tindakan pemimpin populis junjungan mereka yang mencederai kemanusian, mengoyak kebinekaan dan mencederai hukum, mencaci agama lain, dianggap benar, mutlak benar. Konsekuensinya, siapapun yang menentang mereka pasti salah, auto-kafir dan combo-neraka.
Nah, teranyar—setelah rangkaian demo kaum monaslimin-monaslimat tak sesuai harapan para juragan—akal sehatpun dipolitisasi sedemikian rupa sedemikian gila demi selangkangan politik: sama-sama cari makan, sama-sama cari untung, sama-sama melacurkan rasa malu. Pertanyaannya: bagaimana sikap para pembelajar filsafat milenial dan para warganet di tengah pusaran politik akal sehat yang bersimaharajalela parca gerakan populisme Kanan?
Leluhur kami, filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant mengatakan bahwa “Die begierde sättigt man nicht durch Liebe, sondern durch Heirat.” (Orang mengenyangkan nafsu tidak lewat cinta, tapi melalui perkawinan.) Seperti seks, kuasa adalah juga nafsu yang tidak berbentuk dan liar, jika tidak diakomodir dan didisiplinkan secara institusional akan sangat berbahaya.
Hanya lewat lembaga pernikahan nafsu dikenyangkan, hanya lewat prosedur negara hukum yang demokratis kekuasan menjadi rasional. Pernikahan adalah disiplinisasi seks dan demokrasi adalah disiplinanisasi kuasa agar tidak ugal-ugalan dan menjadi angkara murka, meskipun negara tidak pernah sanggup meng-cover hasrat untuk berkuasa (der wille zur macht) para oligark.
Pupulisme, tentu saja, bukan pasangan ideal demokrasi, terutama populisme yang mendapatkan legitimasi dari orang yang mengaku atau diklaim sebagai filsuf oleh gerombolan monaslimin, tapi anehnya tak satupun saya temukan karya filsafatnya. Populisme yang menyamar sebagai gerakan akal sehat, sebagaimana dilontarkan oleh Rocky Gerung bahwa mereka yang demo di Monas (monaslimin-monaslimat) sungguh-sungguh memperjuangkan akal sehat, sebab Monas, demikian lanjut RG, adalah monumen akal sehat.
Mangsa paling empuk bagi populisme Kanan adalah demokrasi elektotal seperti sekarang ini, apa sebab? Karena saat pemilu dan suksesi kekuasaan berlangsung, dana sangat besar dari tangan-tangan predator digelontorkan. Dampaknya? Akal sehat menyusut, sikap kritis mengerdil, mekanisme hukum melemah, para tengkulak merajalela, dan banalitas terjadi di mana-mana.
Satu hal yang harus digarisbawahi, populisme Kanan tidak pernah memperkuat demokrasi, ia justru mengancam keutuhan nasional dengan memanfaatkan “fasilitas” demokrasi, yakni kebebasan menyampaikan pendapat. Nafsu, sebagaimana juga kebencian dan amuk massa, tak pernah dapat bersanding dengan argumen rasional. Jika dipaksakan terjadi perkawinan antara demokrasi dengan gerakan monaslimin yang kini menyamar manjadi politik akal sehat dengan Rocky Gerung sebagai corongnya, perkawinan itu tidak akan pernah bahagia, penuh perselingkuhan dan umbar nafsu kuasa.
Ganjil bin aneh, kaum monaslimin-monaslimat yang notabene cuti nalar (permanen) dan berotak cingkrang tiba-tiba di panggung ILC mengklaim paling berakal dan memperjuangkan akal sehat, tukang asongnya RG tentu saja. Acara ILC, karena memang pesanan, narasumbernya juga pesanan, pemandu soraknya pun pesanan, tukang bikin gaduhnya lagi-lagi pesanan dan memang cari makan di sana (ini tentu harus kita hormati, Saudara-saudara), tidak bisa dikategorikan sebagai “ruang publik” sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Pada episentrum ini, politisasi akal sehat mendapati ruang dan panggungnya. Dan, panggung itu bernama Televisi, juga Media Sosial.
Terus, soal Rocky Gerung yang cari makan dengan retorika dan segala pseudo-diskursus kelas kandang kambing tapi dianggap sebagai ahli filsafat atau fil-syahwat itu bagaimana? Filsuf itu jauh dari jumawa dan kepongahan. Dia bukan filsuf, segala pernyataannya tidak punya basis teori yang ajeg, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis, tidak punya satu karya filsafatpun. Lantas? Ya, kita hormati saja karena dia cari makan di sana dan dengan caranya itu, meskipun tentu saja banyak cara-cara yang mulia dan terhormat untuk sekadar cari makan. Jadi, tidak penting menyoal apakah Monas + ILC = tidak waras atau Monas + ILC = dungu, sebab cara terbaik untuk menolong orang-orang pandir dan ultra-jahiliyah adalah dengan tidak menjadi seperti mereka!
Tak pelak, demokrasi harus toleran terhadap segala sesuatu dan segala kemungkinan, tapi pada saat yang sama demokrasi wajib menjadi intoleran terhadap intoleransi itu sendiri! Inilah akal sehat yang sesungguhnya. Jangan lupa ngopi.
Pengasuh Pesantren Luhur Baitul Hikmah dan menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi Malang. Penulis buku Peradaban Sarung (2018) dan Kondom Gergaji (2018).

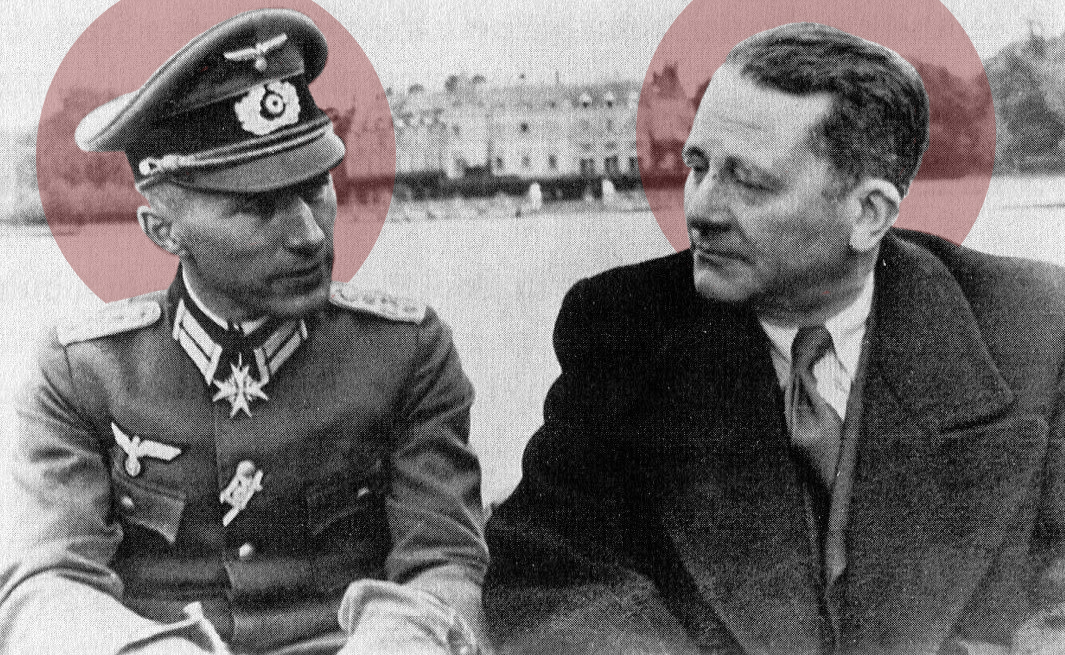











Berikan komentar