Tentu tak bisa dipungkiri bahwa manusia di dalam pengalaman hidupnya pasti akan bertemu dengan banyak dikotomi, baik itu suka atau duka, bahagia atau derita, dan masih banyak lagi, di mana semuanya dapat dijumpai tatkala kita mengarungi seluruh hidup dengan satu tujuan yakni kebahagiaan itu sendiri. Tidak sedikit dari kita akan banyak bertemu dalam sebuah ‘perjumpaan’ dan menemukan bahwa ternyata, untuk mencapai hal tersebut amatlah rumit. Terdapat kelekatan yang perlu dan harus dilepaskan, serta kesinambungan waktu dan perencanaan yang tidak sebanding dengan keinginan kita di dalam kenyataan. Perjumpaan membuat seolah-olah diri merasa tidak mampu hingg terurai tanda tanya mengenai cara menempuh jalan kebahagiaan tanpa harus mengalami penderitaan.
Bagiku kiranya penting untuk melihat kaidah atau pemikiran kaum stoik sebagai sebuah landasan untuk memacu agar semua pengalaman tersebut dapat menjadi berarti. Dengan kata lain pengalaman-pengalaman tersebut walaupun ada tetapi dapat menjadi kekayaan bersama bila diterima sebagai batu loncatan ke arah yang lebih harmoni menuju kebahagiaan itu sendiri. Adapun 4 prinsip etika stoikisme[1] akan menjadi gagasan utama pada tulisan ini sebagai tawaran terkait hidup bahagia menurut stoik
Menerima prinsip Pengada
Dalam pemikiran kaum Stoa, koherensi atau ketersinambungan pada mulanya tak dapat terlepas dari adanya Tuhan sebagai pengada dari seluruh realitas di dunia ini. Melalui padanan ini pula Tuhan dimengerti sebagai logos asal dari seluruh realitas manusia. Terdapat dua kajian untuk memahami Tuhan di dalam pengajaran etika Stoik, bahwa pertama bersatu secara nyata dengan ciptaannya yakni sebagai penyempurna seluruh aktivitas dan kehidupan. Kedua melalui material Ia mengejawantah di dalam keanekaragaman dan juga perubahan.[2] Oleh karena itu pula dengan adanya kedua prinsip atau pikiran stoik terkait adanya Tuhan melalui cara ini adalah sebuah bentuk keserupaan dari seluruh dinamika manusia, sebagaimana sulit ditebak dan bahkan datang tanpa bisa dipastikan bentuknya.
Adagium salah seorang filsuf stoik bernama Seneca berbunyi, “Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima.” [3] Dengan kata lain ungkapan Seneca ini mengisyaratkan kesiapsediaan manusia untuk menanggapi Tuhan beserta seluruh realitas dan dinamika di dalam ciptaan-Nya. Karena itu seharusnya manusia hendaknya tidak hanya berlaku ‘tahu untuk merencanakan’, tetapi juga siap menerima bilamana rencana tersebut gagal akibat misteri yang muncul akibat relasi Tuhan dengan ciptaanNya. Relasi itu mendatangkan hujan, badai, banjir, atau fenomena alam mau tak mau tentu kita harus siap menerima hal tersebut.
Kebijaksanaan sebagai Keteraturan
Pangkal untuk meraih hidup bahagia adalah hidup dengan akal sehat. Kita juga, sebagai makhuk bersifat rasional, harus memilih sesuai dengan apa yang sebenarnya akan terjadi (asalkan kita bisa tahu apa yang akan terjadi, yang jarang kita bisa lakukan – manusia bukan dewa; hasil segala proses menjadi tidak pasti bagi kita) karena ini adalah sepenuhnya baik dan rasional. Ketika kita tidak dapat mengetahui hasilnya, kita harus memilih sesuai dengan apa yang biasanya atau biasanya tujuan alam, seperti yang dapat kita lihat dari pengalaman tentang apa yang biasanya terjadi di alam. Sejauh ini penekanannya hanya pada satu komponen dari rumusan Stoik tentang tujuan atau akhir kehidupan ialah, “Pemilihan rasional dari hal-hal menurut alam.” Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa seleksi rasional – bukan pencapaian – hal-hal inilah yang membentuk kebahagiaan.
Memelihara yang natural
Prinsip ketiga dari paham Stoik adalah kesatuan harmonis dengan alam semesta. Menyesuaikan diri dengan hukum alam akan membuat manusia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada kisah menarik dari Epictetus dimana suatu hari kakinya[4] dipelintir hingga patah oleh tuannya. Namun Epictetus hanya tersenyum dan sedikit pun tidak merasa sedih, khawatir, dan kecewa.[5] Apa yang dilakukan Epictetus merupakan bentuk dari atraxia atau suatu keadaan yang tidak tergantung dengan suatu apa pun. Dari kisah tersebut dapat dikatakan bilamana Tuhan telah berelasi dengan ciptaan-Nya, maka mau tak mau kita harus menghendaki jika seluruh perpaduan alam akan turut serta pula dalam pembentukan diri kita. Jika pohon memiliki satu musim untuk mengugurkan daunnya, demikian pula manusia akan menanti saatnya untuk gugur di medan pertempuran. Karenanya bersiaplah untuk terus berlaku bajik di tengah segala situasi dan siap sedia menerima realitas sebagai kesatuan baik dengan alam dan Tuhan sebagai pengada.
Semua keadaan memiliki sebab
Prinsip ini kiranya menjadi hal utama di dalam etika Stoik. Ia membuat kita berpikir bahwa seluruh kenyataan tak pernah terpecah tanpa adanya koherensi dan keberlanjutan, baik yang disebabkan oleh yang-transendental, maupun alami. Semuanya bersatu demi sebuah pembentukan paripurna. Untuk itu, hal terpenting bukan lagi memikirkan baik dan buruk, senang atau sedih, dan pelbagai dikotominya, melainkan memelihara dan mengetahui bahwa ini akan terjadi. Sehingga akan merangsang manusia mulai berpikir untuk siap terhadap semuanya. Memilih dan mereka-reka melalui akal budi adalah jalan manusia sebagai makhluk berakal, mempersiapkan dirinya secara utuh demi kebahagiaan yang ingin dicapai.
Keempat keutamaan yang diajarkan oleh kaum stoa ini kiranya merupakan sebuah keutamaan, di mana tiap-tiap prinsipnya mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat diraih melalui keharmonisan dan dinamika bersama seluruh ciptaan yang ada di alam. Keutamaan ini sejenak mengajak kita agar tetap mawas dihadapan realitas dan walaupun terdapat dikotomi di dalam pengalaman itu sendiri. Pastikan hal tersebut senantiasa dibimbing oleh rasio, yakni mengajak seluruh keutuhan diri manusia menghayati dan senantiasa siap menerima kehidupan yang telah diatur oleh penguasa dan juga relasinya bersama ciptaan.
[1]Sebuah aliran atau mazhab Filsafat Yunani Kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 SM.
[2]Russels, Bertrand Sejarah Filsafat Barat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 347
[3]Manampiring, Henry Filosofi Teras (Kompas Gramedia: 2018 ISBN 978-6-02412-518-9), hlm. 82
[4]Dilahirkan sekitar tahun 50-an M di Hierapolis, kota Yunani di Asia Kecil, Epictetus menghabiskan sebagian hidupnya sebagai budak Epafroditus, seorang administrator penting di istana Nero.
[5]Wibowo, A. Setyo, “Rangkuman dan Ajaran Stoisisme”, catatan untuk Kuliah I “Seminar Stoicisme” di STF Driyarkara, 27 Januari 2012.

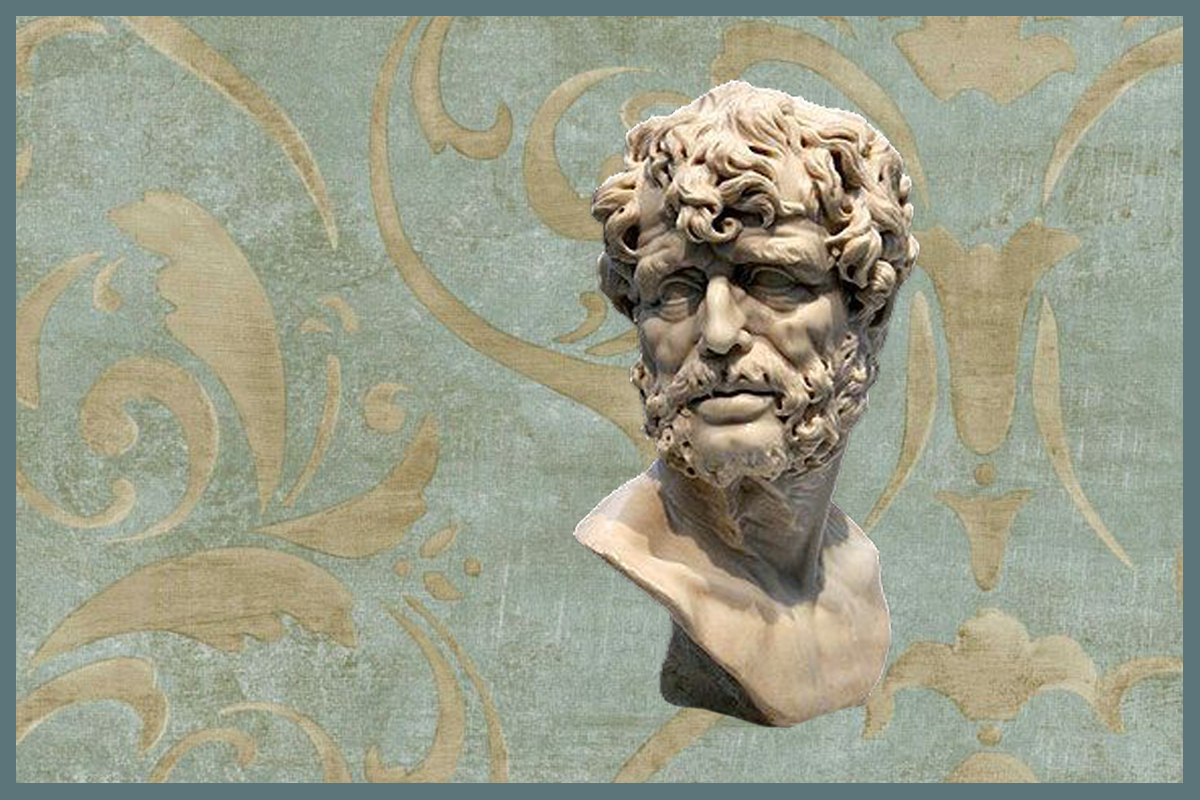







Berikan komentar