Kadang kala ketika kita sedang jenuh dengan rutinitas sehari-hari, alam memberikan tempat bagi kita untuk merasakan ketenangan, keindahan, dan kenyamanan. Apa yang sedang terjadi seakan terlupakan ketika kita menghirup udara pegunungan yang segar, memandang pepohonan, atau mendengar riuh suara ombak di pantai. Tak lupa mengunggah instagram story mengenai cahaya jingga keemasan yang dipancarkan oleh senja, langit yang terbentang kebiruan, dan awan putih yang begitu bersih—dibarengi dengan kutipan-kutipan puitis dan segelas kopi hitam melengkapi kita dalam menghayati alam.
Menikmati alam seperti demikian adalah wajar, terutama bagi saya yang tinggal di perkotaan sering melihat bahwa alam digunakan sebagai fasilitas hiburan. Bahkan pemerintah pun mengklasifikasikan alam sebagai objek wisata. Alam dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik bagi para wisatawan untuk berlibur.
Alam memberikan kita semua keuntungan: ada wisatawan yang berkunjung melepas penat; ada pengelola yang mendapat untung secara ekonomi; bahkan masyarakat sekitar yang ikut meramaikan tempat wisata dengan berdagang. Keuntungan tersebut hanya mungkin didapat karena alam—yang kita sebut sebagai objek wisata—menawarkan keindahannya. Tetapi kerap kali perbuatan kita terhadap alam justru sebaliknya. Sering kali ditemukan banyak wisatawan meninggalkan sampah mereka selepas berkunjung; atau para pedagang sekitar yang membuang bekas dagangannya secara sembarangan.
Laku tersebut sangat terbalik dengan apa yang alam tawarkan kepada kita dan laku tersebut membuat beberapa konsekuensi etis yang akan saya tunjukkan di bawah.
Alam sebagai instrumen
Kalau diliat dari kasus di atas, penghayatan terhadap alam terkesan janggal. Di satu sisi ingin menikmati keindahannya, tetapi pada sikap yang lain justru merusaknya. Dalam situasi tersebut keindahan yang dinikmati dari alam hanyalah sisi lain dari sifat merusaknya. Seperti halnya seorang yang mengklaim telah berkontribusi positif terhadap alam, tetapi pada sikap yang lain dia penyebab kerusakan tersebut. Mengapa seseorang kontradiktif dalam bersikap?
Pertama, tentu di sini ada yang bermasalah terhadap cara seseorang tersebut menghayati alam. Penghayatannya bersifat parsial, tidak lengkap karena tidak ada keselarasan tindakan terhadapnya. Penghayatannya tidak dituntun oleh nilai yang bersifat menyeluruh.
Terlebih lagi kunjungan terhadap alam hanya untuk menyegarkan pikiran dirinya untuk kembali bekerja dengan optimal pada esok hari. Jika seorang pengembang yang menebang hutan untuk membangun infrastruktur berbuat demikian atas nama efisiensi ekonomi, tindakannya tersebut dipengaruhi oleh bagaimana ia memaknai alam, entah alam hanya dianggap sebagai seonggok komoditas baginya, atau sumber aliran rupiah.
Baginya, alam hanyalah instrumen untuk memenuhi tujuan kita. Artinya kita menganggapnya sebagai objek yang dapat diolah semaunya. Diri kita adalah satu-satunya nilai moral yang menjadi patokan dalam memperlakukan alam. Relasi kita dengan alam merupakan hubungan subjek (berkepentingan) dan objek (tak mempunyai kepentingan). Alam merupakan rantai makanan terbawah yang bisa kita konsumsi seenaknya.
Gambaran di atas menjadi sangat penting karena di depan mata kita sudah dihadapkan bencana kerusakan lingkungan, perubahan iklim, atau pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas kita sehari-hari. Semuanya turut berkontribusi dari bagaimana kita hidup, apa yang kita makan, apa yang dikendarai, dan bagaimana sistem ekonomi dan politik kita bekerja.
Oleh sebab itu, sangat krusial untuk melihat kembali bagaimana relasi kita dengan alam. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap alam. Sehingga dapat lahir sebuah nilai sebagai panduan penghayatan terhadap alam dengan cara yang sungguh-sungguh mendikte setiap tindakan individu, kebijakan publik, bahkan sistem ekonomi dan politik kita. Oleh karenanya, kita benar-benar akan bertindak secara konsisten, bahkan sistematis, dengan memahami terlebih dahulu hal-hal yang mendasar.
Pandangan hidup
Seorang filsuf lingkungan Arne Næss (1989) menitik beratkan satu poin penting bahwa:
“I think, important in the philosophy of environmentalism to move from ethics to ontology and back. Clarification of differences in ontology may contribute significantly to the clarification of different policies and their ethical basis.”
Sehingga yang penting untuk diulas pertama kali dalam memahami satu konteks tindakan manusia terhadap alam adalah bagaimana seseorang tersebut memahami realitas (Clarification of differences in ontology). Penghayatan tersebut menuntun seseorang menyikapi, memperlakukan, memahami alam (the clarification of different policies and their ethical basis).
Arne Næss juga mengatakan bahwa seseorang tidak perlu untuk menjadi pelajar filsafat untuk mengubah penghayatan kita kepada alam, tak perlu juga menjadi menteri lingkungan hidup. Justru status subjek sangat tidak penting di sini karena yang dibutuhkan adalah pengalaman langsung untuk bersentuhan dengan alam. Seiring waktu kita akan membukakan diri padanya.
Seperti pengalaman Næss sendiri, ketika muda dia berdiri di tepi pantai memandang dan memikirkan setiap biota laut yang hadir di sana. Pikirannya terproyeksi membayangkan peran terumbu karang di mana tempat ikan berlindung di sana, matahari yang merefleksikan warna air laut yang indah kepadanya, sampai kehidupan terkecil seperti plankton sebagai makanan ikan yang lebih besar ukurannya. Pikirannya melayang dari entitas yang paling kecil bahkan yang tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang penting, ia mengaitkannya ke berbagai entitas yang dilihat di sana. Ia mengamati bahwa entitas tersebut saling terhubung dan berpartisipasi di dalam ekosistem bahkan manusia juga ikut terlibat. Pada momen tersebut, Næss menyadari sesuatu mengenai “hidup” yang begitu luas dan saling terhubung.
Pengalaman tersebut membawanya pada titik di mana terjalin keterhubungannya kepada yang diistilahkannya sebagai “a total view”. Sebuah keadaan kesadaran untuk menyadari di mana entitas organisme (termasuk manusia) selalu berada di dalam “lingkungan” dan berdiri sebagai entitas yang berbeda. Bergesernya kesadaran tersebut meredefinisi pemahaman sebelumnya ke konsep hidup yang saling terhubung nan kompleks. Pada momen tertentu Setiap orang dapat mengalami penghayatan secara demikian dengan membuka dirinya, memperluas konteks dirinya, sadar terdapat kekayaan kehidupan dan sadar selalu menjadi bagian darinya. Penghayatan secara demikian tidak memiliki patokan atau rambu tertentu hanya saja butuh keterbukaan pikiran saja.
Arne Næss terinspirasi dari ekologi ilmu yang menyatakan bahwa terdapat keterhubungan organisme di dalam suatu lingkungan. Kita tidak pernah bisa keluar dari keterhubungan tersebut dan tetap berada di lingkungan yang sama. Perubahan di dalam alam akan turut mempengaruhi kita. Fakta ekologi tersebut juga turut memperluas definisi mengenai kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia tetapi kehidupan organisme-organisme lainnya di mana manusia menggantungkan hidup padanya. Bahkan makhluk yang disebut non-hidup seperti sungai dan laut yang justru di dalamnya terdapat banyak makhluk hidup yang bergantung padanya.
Melalui pengalaman tersebut Næss mengembangkan pemahaman tersebut sebagai cara penghayatan terhadap hidup, atau pandangan mengenai hidup (world-view). Pada situasi di mana telah terjadinya degradasi terhadap alam itu sendiri, krisis, perubahan iklim perlu baginya untuk mengeksplisitkan penghayatan terhadap alam dan menurunkan sebuah sistem norma yang diturunkan dari penghayatan terhadap alam itu sendiri. Sehingga apa yang kita pahami dan apa yang kita lakukan selaras sebagai sebuah gerakan, hal tersebut disebutnya sebagai “deep ecology”.
Perumusan mengenai pandangan hidup dilakukan olehnya dengan membuktikan bahwa manusia tidak lebih sebagai organisme yang hidup berdampingan dengan hidup organisme lain di dalam suatu sistem ekologi. Pembuktian dimulai dengan menolak hubungan subjek dan objek yang melekat di dalam sains dengan menawarkan perspektif relasional.
Pada era di mana kepercayaan diserahkan kepada laku ilmiah yang bersifat objektif—di mana ada subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui—perspektif relasional menawarkan pandangan lain, bukan sekedar subjek dan objek, tetapi subjek ditempatkan pada situasi tertentu sehingga menghasilkan objek demikian. Sebagai perumpamaan, bayangkan jika satu tangan kita dibiarkan di udara dingin dan satu tangan lagi masuk di dalam kantong. Kemudian ketika kedua tangan tersebut dimasukan ke air, air tersebut akan dirasakan hangat dan dingin tergantung situasi tangan sebelumya. Dalam hal ini dapat dirumuskan secara relasional bahwa air tersebut hangat dengan kondisi tangan A, atau air tersebut dingin dengan kondisi tangan B.
Perpektif relasional tersebut menjelaskan bahwa peristiwa yang sama dapat dirasakan secara berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sederhananya tangan tersebut merasakan hal yang sama yaitu air, tetapi disituasikan dengan cara yang berbeda walau pada waktu yang sama. Bagi Næss ini mumbuktikan prinsip non-kontradiksi. Di mana kita bisa mengatakan tidak hangat dan tidak dingin pada satu situasi sehingga yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada kualitas pada alam itu sendiri. Prinsip kualitas tertentu (hangat atau dingin) yang hanya diproyeksikan subjek juga batal. Dalam situasi tersebut yang terjadi adalah setiap hasil dari laku yang kita lakukan selalu mensyaratkan suatu ketotalan dunia, bukan suatu penilaian subjek sendiri. Artinya sesuatu tersebut memiliki hasil demikian atau relasi antara satu dengan lainnya di dalam struktur utuh, lengkap, dan berlangsung.
Penegasan yang dilakukan olehnya berdasarkan perspektif relasionalisme adalah mengatasi pengalaman yang kita rasakan selama ini sebagai kesan subjektif manusia semata. Hal tersebut merupakan cara Arne Næss untuk membentuk satu pandangan hidup yang didasarkan pada kehidupan yang begitu kompleks. Sisi yang Terpenting adalah gambaran mengenai bagaimana kita memproyeksikan diri kita keluar dari diri kita dan menyadari satu lingkungan hidup yang lebih luas (self realization). Jawaban tersebut menjawab satu tujuan khusus di dalam mendefinisikan ulang relasi kita dengan alam.
Pandangan mengenai setiap kesadaran keterhubungan manusia di dalam alam bertemu pada satu titik temu, yaitu selalu terdapat “switching point”, kendati hal itu kompleks atau sederhana. Switching point merupakan titik di mana cara berpikir kita bertransisi dari satu ke kesatuan yang lebih luas. Pada momen tersebut kita melihat diri kita menjadi begitu kecil di hadapan kompleksitas alam. Hal tersebut tidak akan pernah selesai dan selalu berada dalam status “selalu akan dicapai”.
Seperti saat kita melihat gunung, awalnya yang kita lihat hanya keindahan semata, tetapi saat kita membayangkan bahwa gunung bukan hanya sekedar gunung tapi di dalam kemegahannya terdapat fondasi kehidupan; pepohonan yang tumbuh di sekitarnya, yang menjaga kesuburan gunung dan kesejukannya; hewan-hewan yang turut berhabitat di sana; bahkan bakteri-bakteri pada kotoran hewan yang menyuburkan tanah. Di bawah kaki gunung ada manusia yang hidup bertumpu pada ekosistem gunung tersebut.
Relasi manusia dengan alam apabila dihayati dengan cara di atas, relasi kita akan berubah. Relasi demikian menempatkan manusia setara dengan berbagai organisme yang eksis di alam, manusia bagian darinya, dan harus hidup berdasarkan mekanismenya. Dalam hal ini pemahaman demikian melahirkan sebuah nilai sebagai jangkar untuk bersikap dan menghargai setiap kehidupan.
Sistematisasi
Pandangan terhadap hidup (world-view) atau penghayatan terhadap alam dapat memberikan kita suatu kriteria penilaian mengenai satu tindakan tersebut benar, atau tindakan tersebut salah. Dengan mengakui adanya kehidupan yang luas tentu yang dipikirkan adalah bagaimana menjaga kehidupan tersebut.
Di dalam mendikte setiap tindakan atau berhadapan dengan masalah lingkungan yang aktual perlu kita untuk menganalisis masalah menggunakan instrumen cara berpikir yang ilmiah. Agar nilai yang dipegang mengenai pandangan hidup tidak bertabrakan antara satu sama lain dan dapat terus menerus dikembangkan. Oleh karenanya untuk menjadi sistematis perlu adanya turunan logis yang berasal dari pandangan mengenai nilai.
Di dalam mengelaborasi nilai etis dengan sistem normatif, pertama kita perlu merumuskan norma umum yang menjadi rambu-rambu dalam tindakan kita. Kemudian ada hipotesis atau non-normatif (yang praktik) untuk mendukung norma sekaligus dapat juga menjadi inspirasi membentuk suatu norma baru. Semisal norma “Jaga kesehatan tanah!” tentu hipotesisnya dapat berbunyi “Jangan pakai pupuk kimia”; hindari mengolah tanah; dan tanam berbagai jenis tanaman. Dengan turunan tersebut pernyataan akan saling mendukung dan konsisten.
Skema tersebut merupakan bagian dari suatu nilai yang bertujuan menjaga relasi yang seimbang dengan alam. Berdasarkan nilai tersebut kita perlu memprioritaskan dan menyuarakan atau justru mengelaborasi lebih jauh apakah kompatibel dengan sistem ekonomi yang ada, bahkan gaya hidup kita. Di sini penghayatan kita terhadap alam sudah sampai pada pengetatan terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Sistem normatif tersebut mencegah agar perilaku kita tidak tumpang satu sama lain terhadap alam.
Meredefinisi ulang relasi manusia dengan alam dan menyistematisasi tindakan bukan sekedar mengatasi masalah yang ada sekarang ini, tetapi menawarkan cara hidup baru yang terus berkelanjutan. Sifat tidak konsisten dari cara hidup yang telah dilalui manusia harus dihindari. Bukan hanya berkutat pada solusi cepat atau bertindak tambal sulam yang hanya menghasilkan hal hal yang hanya bersifat sementara, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, koheren, dan mendasar.
Referensi:
Arne Næss (1989). Ecology, community, and lifestye: Outline of an ecosophy. Cambridge: Cambridge University Press.


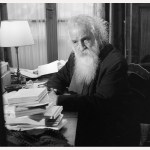






Berikan komentar