Skizoanalisis pertama kali dicetuskan oleh Gilles Deleuze dan Félix Guattari dalam Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1972). Secara sederhana, kerangka teoretis ini menggugat ide-ide yang disepakati seputar gangguan kesehatan mental, subjektivitas, dan struktur sosial. Kesepakatan di isu-isu tersebut dalam nalar publik (common sense) dirasa masih tersandera oleh penjabaran mengenai kecenderungan perilaku individu via psikoanalisis klasik. Jika psikoanalisis klasik melibatkan diri pada relasi familial(kekeluargaan)—dengan kata lain, Oedipal—, skizoanalisis menawarkan subjek dalam bentuk relasi yang melampaui diri (transendental) dan terjadi di ruang sosial-politik (materialis).
Sebagai contoh, anggapan bahwa perilaku tertentu seseorang didasarkan pada isu parental seperti daddy-issues atau mommy-issues. Penjelasan tersebut selaras belaka dengan psikoanalisis klasik yang membatasi penelusuran gangguan kesehatan mental pada hubungan familial. Praktis, penjelasan tersebut membatasi pula kedalaman subjektivitas dan struktur sosial lain sebagai penjelasan alternatif. Skizoanalisis kemudian hadir untuk menawarkan perangkat penelusuran yang menggugat kedangkalan psikoanalisis.
Skizoanalisis melibatkan libidinal investment dalam penyusunan tesis-tesisnya. Libidinal investment (selanjutnya disebut libi-in) yakni taklik (attachment) yang begitu kuat secara emosional terhadap suatu monumen, seperti ide, konsep, atau tokoh. Contoh sehari-hari libi-in barangkali muncul dalam patriotisme. Patriotisme sebagai ideologi adalah wujud dari taklik emosional atas ide dan konsep kebanggaan atas suatu bangsa/negara.
Biasanya, patriotisme mempunyai wajah berupa tokoh maupun simbol. Tokoh, simbol, ide, dan konsep inilah yang menjadi monumen di mana identitas dan perilaku ditahbiskan (invested). Karena sifat pentahbisan (investment) ini emosional, libidinal didorong oleh hasrat primal, yang mungkin tidak disadari sepenuhnya. Pelecehan atas monumen-monumen tersebut dianggap mengganggu dan reaksi emosional seperti tersinggung (agitated) bisa saja terjadi. Saluran ketersinggungan mewujud dalam perlawanan atau tindakan agresi lain.
Tesis-tesis skizoanalisis via libi-in memberi alternatif penjabaran atas pertemuan tindak dan perilaku tersebut dalam ideologi. Tesis-tesis tersebut membincangkan bentuk relasi yang lebih luas (transendental dan materialis) ketimbang masalah parental atau kurangnya perhatian papa mama. Melalui libi-in, skizoanalisis merumuskan empat tesis utamanya. Keempat tesis tersebut adalah:
- Tesis pertama, libi-in tak-sadar selalu bersifat sosial dan menanggung wilayah sosio-historis. Libi-in tak-sadar tidak mengada begitu saja tanpa karakteristik. Karakteristik libi-in selalu bersifat sosial (mawas akan liyan) dan praktis berada pada medan sosio-historis.
- Kedua, libi-in tak-sadar atas kelompok atau hasrat berbeda dengan investasi prasadar atas kelas atau kepentingan. Maksudnya, libi-in tak-sadar biasanya berkaitan dengan identitas asali atau hasrat dasar (primal), sementara investasi prasadar dikonstruksikan oleh pengetahuan—yang kemudian berkembang menjadi kesadaran kelas dan identifikasi kepentingan. Bukan berarti keduanya lebih unggul atas satu sama lain, melainkan sekadar berbeda.
- Tesis ketiga, libi-in non-familial di wilayah sosial punya keterhubungan primer dengan libi-in familial. Artinya, bagaimana taklik dibentuk di wilayah sosial adalah hasil didikan/taklik di wilayah keluarga, dan vice versa. Skizoanalisis tidak menganulir adanya hubungan familial yang menjadi motif dari psikoanalisis. Skizoanalisis menolak ide bahwa keluarga merupakan bagian dari himpunan masyarakat yang lebih besar. Hubungan keluarga dan implikasi oedipal hadir sebagai salah satu nodus/titik yang memiliki keterhubungan primer dengan masyarakat/komunitas sosial sebagai titik lain. Titik-tersebut kemudian saling terangkai dalam jejaring yang turut memproduksi hasrat pra-individu serta sosial. Pembedaan bertingkat atas keluarga serta masyarakat adalah semu belaka—atau dalam istilah Deleuze-Guattari, pseudo-oposisi.
- Terakhir, libi-in sosial dibedakan menjadi dua kutub: kutub paranoia reaksioner dan kutub skizoid revolusioner. Kutub paranoia reaksioner sendiri berarti bahwa kerocetan menghasilkan ketakutan sehingga melahirkan ideologi yang hanya mewajarkan sesuatu yang telah dikenali, seperti fasisme dan rasisme. Di sisi lain, kutub skizoid revolusioner mewajarkan cara pandang dunia yang secara radikal berbeda, di mana ideologi tumbuh berdampingan seperti jejaring.
Keempat tesis tersebut sederhananya menegaskan bahwa ketak-sadaran yang menjadi wilayah libi-in beroperasi bukan sekadar gudang memori dan hasrat yang ditekan/direpresi. Ketak-sadaran adalah sebuah mesin dinamis yang terus menerus memproduksi moda mengada dan pemikiran baru. Sudut pandang skizoanalisis menolak ide tentang diri tunggal dan tetap. Malah, skizoanalisis mendorong serta menyambut kejamakan (multiplisitas) dan kealiran (fluiditas) dari subjektivitas.
Skizoanalisis menjadi berbeda dari psikoanalisis karena skizoanalisis merespon kekurangan psikoanalisis. Kekurangan yang dimaksud adalah ketimpangan relasi otoritatif antara pasien dengan psikoanalisis dalam praktik, serta kompleks Oedipus (Bertens: 2006) yang menjadi titik mula pemeriksaan. Skizoanalisis dikembangkan untuk memberi agensi (assemblages/agencements) pada pihak terkait dan mencari titik koordinat pemeriksaan baru yang tidak tersentuh sebelumnya. Jika psikoanalisis klasik secara tipikal berupaya menormalkan/menyembuhkan penyimpangan, skizoanalisis malah mendobrak struktur dan status quo.
Praktis, psikoanalisis tipikal berkutat dengan individu dan perkara Oedipal untuk menjelaskan perilaku dan penyimpangan, skizoanalisis menariknya pada perkara organisasi sosial yang me- dan di-pengaruhi individu, subjektivitas, dan hubungan familial/kekeluargaan. Inilah yang kemudian menjadi dasar tesis ketiga. Konsep ini menjadi sentral pada skizoanalisis dan diberi nama rimpang (rhizome).
“Skizoanalisis […] tidak punya makna lain: bangun rimpang!” (Deleuze dan Guattari: 1987). Rimpang, dalam skizoanalisis, adalah sebuah metafora dari jaringan non-hierarkis serta saling-terhubung yang terus tumbuh dan meluas tanpa akar terpusat atau muasal. Jika digambarkan, layaknya dendrit pada anatomi sel saraf yang berbentuk radial, alih-alih linier. Konsep ini berbanding terbalik dengan struktur seperti pohon yang biasa digunakan untuk mewakili model pemikiran atau organisasi. Rimpang mengisyaratkan kejamakan koneksi dan kemungkinan, menyilakan lahirnya bentuk-bentuk pengetahuan dan ekspresi baru nan tidak terduga.
Dari rimpang, berkembang pula deteritorialisasi. Gagasan deteritorialisasi merujuk kepada proses pembebasan dari kotak dan struktur termapankan, memberi jalan kepada penciptaan teritori dan moda mengada baru (reteritorialisasi). Deteritorialisasi bukan hanya perkara menolak sejarah atau masa lalu, melainkan proses produktif yang melibatkan rekonfigurasi/penyusunan ulang elemen-elemen yang telah ada menjadi bentuk-bentuk yang lebih baru (Negri: 1991).
Deteritorialisasi terbagi menjadi deteritori relatif dan deteritori absolut. Deteritori relatif selalu ditemani reteritorialisasi atau penyusunan ulang. Sedangkan, deteritori absolut kemudian terbagi menjadi positif—di mana jagad imanensi atau ketunggalan hadir—dan negatif—di mana proses subjektifikasi, atau peralihan objek dipertimbangkan menjadi subjek, mengambil tempat.
Perangkat lain yang menjadi bahasan diskusi skizoanalisis adalah jasad-nir-organ (corps sans organes) dan nomadisme. Jasad-nir-organ (selanjutnya disebut JnO) pertama kali dicetuskan dalam naskah drama gubahan Antonin Artaud berjudul To Have Done With the Judgment of God (1947) yang kemudian dikembangkan oleh Gilles dan Deleuze. Sejauh pemahaman penulis, JnO mengandaikan jasad yang merdeka dari kerja-kerja organ yang saling bergantung untuk mendukung eksistensi jasad/homeostasis. Contoh dan implikasi linguistiknya barangkali terletak bagaimana gumaman terucap—gumaman mempunyai makna dalam kerja percakapan, namun belum tentu jika tertera dalam teks.
Nomadisme, di sisi lain, adalah cara hidup yang dicirikan oleh gerak, perpindahan, dan perlawanan atas identitas yang ajeg (Grosz: 1994). Nomadisme bukan hanya tindak fisik untuk berkelana, melainkan keadaan nalar yang memeluk kealiran eksistensi dan menolak belenggu dominan kewilayahan/teritorial.
Seperti yang tertera pada tesis pertama dan kedua, skizoanalisis menganjurkan pendekatan yang lebih terbuka dan cair atas subjektivitas dan organisasi sosial. Teori ini menentang wacana dominan seputar kuasa dan kendali, mendorong individu untuk menjelajahi hasrat dan potensinya. Di sinilah letak kritik atas kapitalisme pada skizoanalisis, yang melihat kapitalisme sebagai sistem yang berusaha mengendalikan dan mengeksploitasi hasrat.
Salah satu kontribusi penting skizoanalisis adalah kemampuannya untuk merangkai kembali ide tentang gangguan kesehatan mental. Skizofrenia sebagai sebuah kondisi didudukkan kembali. Di samping sebagai gejala patologis, skizofrenia mewakili neurosis yang dipelihara kapitalisme untuk menjaga kenormalan. Akibatnya, penanganan dan aksesibilitasnya selalu menjadi nomor dua. Skizoanalisis menawarkan alternatif radikal via perawatan terhadap sang liyan. Perspektif ini mendorong dampak yang lebih dalam di bidang psikiatri dan psikologi, menuntun pada pengakuan yang lebih luas atas keragaman pengalaman manusia dan keterbatasan kategori-kategori diagnostik tradisional.
Hadirnya skizoanalisis bukan berarti tanpa kritik. Para sarjana feminis berargumen bahwa kerangka teoritis skizoanalisis mempunyai potensi mempertajam stereotip gender dan mengabaikan tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan di masyarakat yang patriarkis (Braidotti: 1994). Kritik ini dikarenakan skizoanalisis dianggap mengabaikan sejarah relasi kuasa di seputar perempuan dan urung memproblematisirnya. Skizoanalisis, sebagai ekspansi dan kritik atas psikoanalisis, praktis mewakili pula sejarah wacana kesehatan jiwa yang notabene seksis, seperti diagnosa histeria (Maines: 1999). Sebab itulah, Deleuze dan Guattari dianggap kurang terlibat dalam teori feminis kala mengembangkan skizoanalisis. Kritik lainnya, nomadisme dan subjektivitas skizofrenik yang dibawa oleh skizoanalisis dianggap oleh para sarjana feminis kurang memadai dalam menjelaskan konteks spesifik dan dinamika kuasa yang dialami oleh liyan. Akibatnya, skizoanalisis justru menjadi bumerang yang mengempiskan—dan berpotensi mengabaikan—pengalaman sang liyan (Sholtz, et al: 2019).
Terlepas dari kritik-kritik tersebut, skizoanalisis tetap menjadi perangkat yang berharga untuk memahami subjektivitas dan masyarakat. Penekanannya terhadap kejamakan, kealiran, dan potensi transformatifnya menawarkan alternatif berdaya atas wacana dominan di zaman kita.
Hamzah
Lebih suka menyebut dirinya bermatra jamak seperti larik Walt Whitman. Buruh media dan komunikasi. Menulis Agen Koming (2022) dan menerjemahkan 2889 dan 4.0 Fiksi Sains Lainnya (2023). Dapat ditemui di https://hamzah.id/

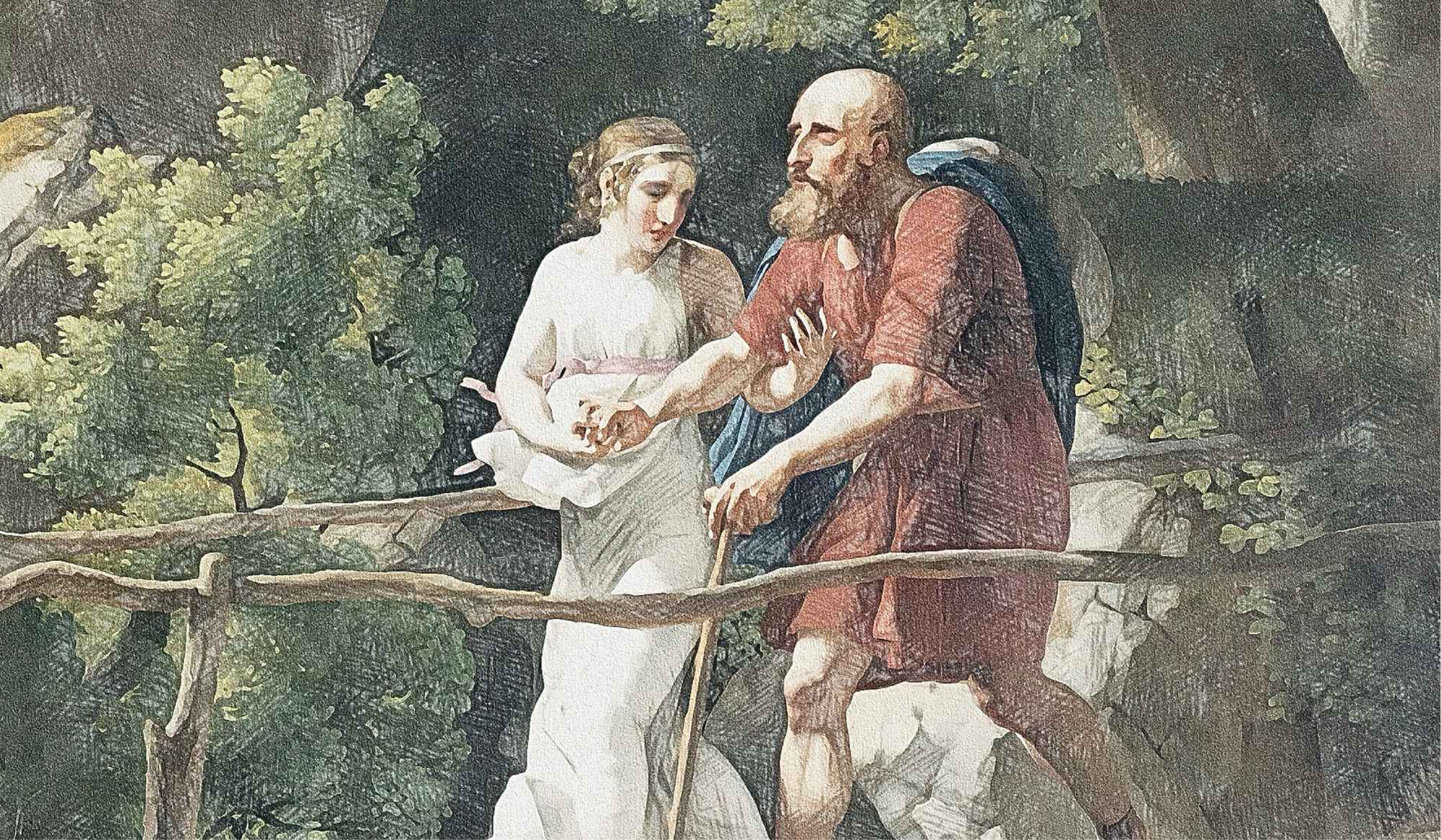






Berikan komentar