Membaca Al-Munqidz Min Adh-dhalal karya Al-Ghazali yang telah diterjemahkan oleh Ach. Khoiron Nafis menjadi salah satu alternatif dalam mempelajari epistemologi Ghazalian dan seturut sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya kerangka berpikir tersebut. Buku tersebut tersusun dalam surat-surat penulis kepada “saudara se-agama” yang kini tertuju kepada siapapun Anda bahkan yang berjarak sepuluh abad dari masa hidup Al-Ghazali.
Dalam “Metode Kaum Sufi”, Al-Ghazali menggambarkan dirinya sedang tenggelam dalam pertanyaan hingga tubuhnya tidak dapat bergerak, pun menelan sepotong roti dan air minum. Al-Ghazali berniat untuk menggambarkan kesulitannya dalam memurnikan kebenaran dari pertikaian beberapa mazhab pemikiran yang bermunculan pada eranya. Melalui pengamatannya, ia mengklasifikasikan para pencari kebenaran menjadi empat golongan yaitu kaum teolog (al-Mutakallimun), kaum batiniyyah (al-Bathiniyah), kaum filosof (al-Burhan), dan kaum sufi (musyahadah dan mukasyafah).
Setelah mengenali keempat kelompok tersebut, kegelisahan Al-Ghazali berlanjut dalam pencariannya menemukan kaidah tertinggi. Pengalaman bertemu dengan berbagai golongan menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia terlebih dahulu harus memahami perangkat ilmu pengetahuan sehingga ia mampu mengetahui keberadaan kebenaran dan lalu menyelaminya. Kenyataan bahwa untuk mengetahui perangkat tersebut manusia terlebih dahulu harus menyadari benar-benar keberadaan dirinya sendiri. Proses ini menjadi tantangan awal dalam perjalanan epistemologis Al-Ghazali. Dalam Al-Munqidz Min Adh-dhalal, ia menyatakan bahwa pada mulanya terdapat perdebatan antara pengetahuan rasional dan pengetahuan inderawi (yang pada saat ini umum dikenal sebagai empirisisme) di dalam dirinya. Baik rasio maupun indera saling berlomba mengunggulkan diri dan kian menjatuhkan sehingga Al-Ghazali yakin bahwa terdapat suatu hal yang lebih tinggi dibanding keduanya. Dalam percakapan imajinatif tersebut, Al-Ghazali memperhitungkan keduanya. Namun, sekaligus juga menafikannya. Hal tersebut terjadi karena menurut Al-Ghazali pertikaian rasio dan indera tersebut merupakan pertentangan di antara dua hal berbeda namun dalam kelompok yang sama.
Al-Ghazali memiliki pandangan yang senada dengan John Locke1 mengenai kondisi awali manusia. Locke mengandaikan manusia pada mulanya merupakan kertas kosong atau disebut dengan tabula rasa. Dalam pernyataan yang berbeda, pokok pikiran keduanya mengenai kondisi asali manusia senada. Demikian dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam “Hakikat Kenabian” bahwa:
Ketahuilah, sesungguhnya manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan kosong, tanpa pengetahuan tentang berbagai alam yang dimiliki Allah Ta’ala.”
Manusia yang sebelumnya kosong tersebut diberkati dengan beberapa perangkat sehingga dapat menerima informasi yang disampaikan oleh sumber dari segala sumber. Dalam penjelasan Al-Ghazali manusia memiliki empat perangkat internal yaitu indera, tamyiz, rasio dan akhirnya intuisi (dzauq). Perangkat terakhir inilah yang digunakan untuk kaum sufis agar hidupnya kembali kepada hakikat kenabian. Hakikat kenabian (haqiqat al-nubuwah) yang dimaksud bukanlah kondisi dimana manusia sekedar bersuci melainkan juga menjadi pribadi yang dapat menerima dan menyebarkan pesan Allah. Dengan demikian, pencarian Al-Ghazali mengenai mazhab pengetahuan terhenti pada sufisme yang berlandaskan pada metode pendekatan intuitif untuk mengenali keberadaan kebenaran yang sejati.
Di antara ilmu pengetahuan yang diamati oleh Al-Ghazali terdapat ilmu filsafat yang memiliki kekurangan dan kelebihan sedemikian dijelaskan olehnya:
Aku tahu persis bahwa seseorang yang tidak menyadari kesalahan suatu pengetahuan (tentang filsafat), berarti tidak dapat mengetahui puncak pengetahuan tersebut.
Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan mengenai kerancuan filsafat dalam menolak Tuhan serta rincian dari ilmu yang dipelajari dalam filsafat. Pada abad ke-11 Masehi, Al-Ghazali mempelajari para filosof Yunani kuno dan klasik hingga memperoleh kesimpulan bahwa mereka—para filosof Yunani—sering kali mengesampingkan Tuhan dalam proses pencariannya. Bagi Al-Ghazali, perlawanan filosof Yunani kepada eksistensi pencipta atau para dewa dianggap sebagai sikap materialistis (dahriyyun) dan mereka divonis sebagai ateis atau zindiq. Selain itu, terdapat juga para filosof yang mengingkari keberadaan alam lain di luar bumi dan langitnya sehingga disebut sebagai kaum naturalis (thabi’iyyun). Namun, masih ada filosof Yunani klasik yang percaya mengenai keberadaan Tuhan, yang dinamakan oleh Al-Ghazali sebagai kaum Ilahiyyun. Para filosof ini di antaranya ialah Socrates, Plato dan Aristoteles. Ketiga kelompok tersebut melakukan pencarian melalui bidang-bidang yang berbeda namun saling berhubungan. Ilmu-ilmu tersebut di antaranya adalah ilmu Riyadhiyyah (matematika), Mantiqiyyah (logika), Thabi’iyyah (pengetahuan alam), Ilahiyyah (metafisika), Siyasiyyah (politik), dan Khaliqah (etika).
Sebagai filosof dan mistikus, Al-Ghazali berhasil memadukan metode filsafat skeptisisme dalam pencarian tebing dan palung semua pengetahuan yang ia ketahui. Ia bermula dengan mengajukan pertanyaan atas keyakinan sementara dari tiap-tiap ilmu pengetahuan. Melalui metode kritis tersebut, akhirnya ia (dengan diimbangi sikap dan perilaku orang beriman) berhasil menemukan bahwa intuisi merupakan gerbang menuju penerimaan pengetahuan dari Yang Maha Kuasa bahkan manusia tidak hanya menerima melainkan mampu mewartakannya kepada sesama manusia apabila intuisi telah terbuka. Intuisi tersebut walaupun telah ada namun harus diaktifkan dengan jalan kerinduan untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Jalan ini yang dapat membimbing manusia menuju kesatuannya dengan Yang Agung, yaitu melalui jalan cinta kasih dan penghormatan tertinggi atas kemuliaan Tuhan. Namun, hasil yang diperoleh—dari pencarian Al-Ghazali—menuai kritik tajam terutama karena menafikkan ilmu-ilmu logis seperti yang telah dijabarkan oleh filosof Arab pendahulunya.
Hal yang terjadi pada Al-Ghazali memiliki kemiripan dengan pengalaman dan rumusan Agustinus, seorang Bapa Gereja dari Hippo (sekarang wilayah di Aljazair Afrika Utara). Agustinus merupakan mistikus Gereja yang memiliki ide dasar bahwa rasio manusia merupakan perangkat tertinggi yang dapat digunakan untuk menerima dan mengelola pengakuan atas Allah. Konsep Divine Illumination merujuk pada wahyu Tuhan dan iman. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang berkaitan erat satu sama lain. Fides et ratio dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan karena iman hanya bisa menjadi pengakuan akan rahmat Tuhan yang benar apabila ia berada dalam asuhan rasio manusia. Sementara itu, rasio yang sehat merupakan nalar yang bergantung dari rasa percaya atas keagungan Tuhan dalam menciptakan segala eksistensi bagi dunia. Perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Agustinus terletak pada perangkat yang mampu menerima pengetahuan atau pancaran dari Tuhan. Dalam konsep Agustinus, perangkat yang mampu menyerap wahyu dan menerjemahkan rasa setia atau cinta kasih ialah rasio. Sementara Al-Ghazali berpendapat bahwa intuisilah yang merupakan perangkat tertinggi dalam tugasnya untuk mengenal wahyu Allah serta seluruh eksistensi metafisik .
Persamaan lain di antara keduanya adalah penekanan terhadap perubahan sikap. Sikap mencerminkan keimanan dan begitu pula sebaliknya. Sikap manusia beriman selalu membatasi dirinya untuk berada dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran iman. Selain itu, tubuh menjadi tanggung jawab manusia kepada Tuhan sehingga tidak dirusak semata karena ia adalah milik manusia untuk sementara saja. Konsep manusia tanpa rasio bagi Agustinus atau tanpa intuisi bagi Al-Ghazali merupakan manusia yang tidak mampu merawat diri dan imannya. Manusia tersebut tidak dapat memahami Tuhan hanya dengan perangkat paling dasar misalnya indera semata. Hal tersebut dinarasikan oleh Al-Ghazali seperti seseorang yang mempelajari Al-Quran dan hadits serta menekuninya. Dengan demikian, ia akan mengetahui secara pasti bahwa Nabi Saw memiliki derajat kenabian yang paling tinggi. Pengetahuan ini dinamakan dharuri. Selanjutnya apa bila seseorang tadi menyakini apa yang ia ketahui dan bertekun untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Saw maka ia akan menerima proses dzauq. Proses intuisi ini menyertakan dalil keimanan dalam menjawab permasalahan isykal dan syuhbat.
Bagi sistem filsafat modern, peristiwa mujizat tidak dapat dijelaskan secara nalar kecuali diteliti terlebih dahulu melalui sains atau ilmu atomis. Namun, hal tersebut sering kali justru merujuk pengetahuan manusia terhadap kemungkinan yang terbatas dan positivistik. Pengandaian digambarkan dalam pernyataan bahwa suatu ketertarikan disebut sebagai daya tarik, atau chemistry. Dalam contoh ini peneliti dapat menghubungkan ketertarikan seseorang kepada lawan jenis akibat dari ketertarikan satu pihak terhadap aroma badan maupun raut wajah namun hal tersebut tidak berarti bahwa persahabatan atau cinta dapat dibentengi oleh batas proses kimiawi maupun fisika. Terdapat proses lain yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui penelitian mendetail dan ribuan trial and error di dalam ruangan steril. Demikian pula terjadi apabila manusia berusaha mencari jawaban mengenai kehidupan setelah kematian atau asal mula kehidupan. Beberapa golongan menolak ajaran Al-Ghazali sebagai ilmu dalam filsafat melainkan sebagai ajaran mistik. Namun, pandangan demikian melewatkan—atau dengan sengaja—mengesampingkan metode skeptis-kritis Al-Ghazali yang digunakan dalam pencarian menuju ilmu sufistik.
Filsafat tidak hanya memperhitungkan hasil yang diperoleh namun sebaliknya: menjunjung tinggi proses pencarian dan perenungan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam perjalanan nalar. Satu rindu akan kebenaran, satu niat mempertanyakan, dan satu langkah pencarian dapat menuntun manusia menuju gelapnya belantara dan terangnya padang dalam perjalanan mencari hakikat yang sesungguhnya. Demikian pula yang dialami Al-Ghazali dalam kehidupannya:
Mula-mula hal yang harus kutemukan adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, karenanya aku harus mengetahui apakah esensi pengetahuan itu?”

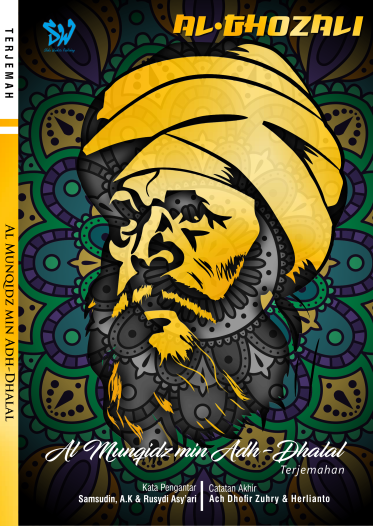















Berikan komentar